Proyeksi Status Bahasa Indonesia di Dunia Internasional melalui Revitalisasi Legenda Dunia Kemenyan dan Kapur Barus
Dua komoditas perdagangan—kemenyan (styrax benzoin) dan kapur barus (campher)—mulai mendunia jauh sebelum abad Masehi. Perdagangan internasional ini diketahui membawa bibit-bibit kebahasaan dunia yang membekali bahasa Indonesia.
Upaya revitalisasi legenda dunia kemenyan dan kapur barus diharapkan dapat menghasilkan dua hal penting. Pertama, refleksi kebangsaan atas simbol jati diri keindonesiaan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika; kedua, proyeksi kebahasaan atas status bahasa Indonesia yang sedang diikhtiarkan di dunia internasional melalui program pemajuan bahasa dan sastra.
Program penginternasionalan bahasa Indonesia—seturut dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor. 57 Tahun 2014 (Pasal 31 ayat (1) )—juga membidik dua sasaran strategis. Pertama, jati diri bangsa Indonesia yang ditunjukkan pada dunia internasional; kedua, daya saing bangsa Indonesia yang dikuatkan dalam kebinekaan global. Konsep dua sasaran itu tampak bersifat kumulatif: berjati diri terlebih dahulu; kemudian, mampu berdaya saing. Bukan sebaliknya.
Citra diri bangsa
Cerita kemenyan dan kapur barus memberikan petunjuk reflektif mengenai citra diri pada bangsa Indonesia yang secara geneologis tumbuh dari bibit-bibit kebangsaan yang sangat unggul di dunia modern pada saat ini. Pada masa silam—diproyeksi telah mulai terjadi 2500 sebelum Masehi (temuan Tumanggor, 2017; 2019)—komoditas unggulan Nusantara ini diperdagangkan dengan bangsa Cina, Eropa, dan Arab di Barus: sebuah kota pelabuhan laut di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bangsa-bangsa besar itu terbukti hadir mewarnai bangsa Indonesia.
Jaringan perdagangan kuno tersebut menunjukkan eratnya hubungan antarbangsa, tidak hanya dalam kontak dagang, tetapi juga kontak budaya dan bahasa. Artefak kebahasaan dari jaringan itu ditemukan oleh Rusmin Tumanggor, misalnya, pada ekspresi teologis Hong dan Hah dalam agama RU: cikal bakal agama Khung Hu Cu di Indonesia. Dalam kaitan itu, terdapat catatan penting bahwa agama Khung Hu Cu dianut pertama kali oleh dinasti kedua di Tiongkok.
Selain bangsa Cina, termasuk juga bangsa Eropa dalam jaringan perdagangan kemenyan dan kapur barus. Bangsa Eropa itu ditemukan dengan hadirnya para pedagang Yahudi berbahasa Ibrani (Hebrew). Artefak kebahasaannya berupa ekspresi teologis seperti Ya Sah; Ya Suh; Ya Suah. Ekspresi kebahasaan itu sekarang masih hidup dalam praktik budaya masyarakat Barus, khususnya untuk mengusir penyakit/sumber penyakit. Lebih lanjut, temuan Tumanggor mengonfirmasi adanya kontak budaya Hindu dari India dalam kontak dagang itu di Barus.
Melalui dunia perdagangan pula, kehadiran bangsa Arab tertelusur. Kafuuran (?????????) yang diartikan ‘kapur barus’, antara lain oleh Bahrum Saleh (2020:57) merupakan kosakata bahasa Indonesia yang tercatat di dalam kitab suci Al-Qur’an (Surat 76: Al-Insan ayat (5)). Pemanfaatan kapur barus untuk memandikan jenazah juga diceritakan dalam Hadits Rasulullah saw. (Himpunan Putusan Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1967 dalam Saleh, 2020).
Pemandian jenazah dengan kapur barus sebagai syarat wajib tersebut sekarang masih dipraktikkan di dunia Islam. Praktik itu merupakan bukti kuat bahwa kapur barus (yang asli, bukan tiruan atau campuran (sintetis), menurut Tumanggor (2019)) telah lama diperdagangkan di Arab (Mekah dan Madinah) pada masa keislaman Nabi Muhammad saw. (abad ke-7). Bahkan, melalui analisis kritis atas kandungan kitab suci dan hadis, para pedagang Arab diperkirakan telah biasa berniaga dan datang ke Barus sebagai pusat perniagaan itu sebelum abad ke-7.
Citra bangsa Indonesia dari cerita kemasyhuran Barus sebagai kawasan perdagangan kemenyan dan kapur barus dapat diketahui lebih mendalam melalui bacaan internasional (Azhari, 2019). Dalam kritik sumber bacaan sejarah, Ichwan Azhari mengungkap kembali catatan Ambary (1998) mengenai berita dari Cladius Ptolemaeus pada abad ke-2 Masehi dalam sebuah buku geografi yang menyebut nama Barus sebagai Barousai. Nama Barus (baca juga: Sinar Basarshah, 2002) diketahui pula dari cerita bahwa raja-raja Firaun Mesir kuno—ketika meninggal dunia—dibalsam dengan kapur barus. Dari beragam sumber (antara lain dari Arab, Persia, Armenia, dan Tamil), Azhari juga mencatat nama lain dari Barus itu sebagai Fansur/Fansu’er/Pancur.
Mata rantai kebahasaan
Nama Fansur (Fansuri) telah lekat pada ulama dan penyair terkemuka Hamzah Fansuri (Al Attas, 1970 dalam Tumanggor, 2017:116). Kepenyairan ini merupakan mata rantai kebahasaan yang amat penting bagi bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh syair sufistiknya.
Hamzah Fansuri di negeri Melayu
Tempatnya kapur di dalam kayu
Asalnya manikam di manakan layu
Dengan ilmu dunia di manakan payu
(dikutip dari Ikatan-Ikatan XV dalam Abdul Hadi W.M., 2002; 2020)
Hamzah Fansuri—Hamzah dari Barus—diakui di dunia kesusastraan sebagai pencipta pertama syair Melayu (Teeuw, 1994). Puisi empat baris bersajak seperti contoh di atas ternyata digemari oleh sastrawan Nusantara sejak abad ke-17. Pada abad ke-16, bahasa Melayu yang terkembang dari Barus itu mencapai puncak status yang oleh Hadi (2002) dinyatakan: “bahasa pergaulan utama penduduk kepulauan Nusantara di bidang perdagangan, keagamaan, dan intelektual”. Perdagangan pada masa itu tentu berupa komoditas utama kemenyan dan kapur barus.
Dari bidang keagamaan, karena kesufian Hamzah Fansuri, konsep Al-Qur’an dan falsafah Islam telah terserap ke dalam perbendaharaan kata yang turut membekali bahasa Indonesia. Dalam studi hermeneutika terhadap karya Hamzah Fansuri itu, Hadi (2020:452—468) mengurutkan secara alfabetis ratusan kosakata (dari abad hingga zuhur) yang bersumber dari bahasa Arab di samping sumber kosakata yang digunakannya dalam berkarya dari bahasa Melayu dan Jawa.
Karya-karya intelektual Hamzah Fansuri merupakan karya tulis ilmiah “seminal” dalam jagat keilmuan di tanah air Indonesia. Salah satu ciri keilmiahan itu ialah adanya reduplikasi proses ilmu. Dalam kaitan itu, tulisan Hadi (2021) yang bertajuk “Gema Sufi dalam Sastra Indonesia: dari Sanusi Pane sampai Sutardji” menggambarkan betapa gerakan romantisme sufistik Hamzah Fansuri tereduplikasi dalam mata rantai kebahasaan selama empat abad (sejak abad ke-16).
Mata rantai itu memang tersambung hingga tahun 1970-an ketika julukan “Presiden Penyair Indonesia” disematkan pada tokoh sastra Sutardji Calzoum Bachri. Titik kemajuan sastra Indonesia itu juga merupakan proyeksi atas sambungan mata rantai sebelumnya dari pembibitan bahasa dan sastra Melayu modern di Barus tersebut hingga era Pujangga Baru pada tahun 1930-an. Selain tokoh sastra Pujangga Baru—pada era pra-Kemerdekaan Republik Indonesia ini—Sanusi Pane juga tokoh penggerak lahirnya kembali bahasa (persatuan) Indonesia pada tanggal 2 Mei 1926.
Bahasa Indonesia dilahirkan kembali dan dikukuhkan kelahirannya dalam teks Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam kaitan itu, Sanusi Pane (baca Nasititi, 2013) berpandangan bahwa landasan Indonesia memang telah ada sebelumnya sebagai alas asimilasi dengan semua pengaruh asing. Cerita Barus sebagai kancah lebur (‘melting pot’) dalam legenda dunia kemenyan dan kapur barus merefleksikan pengaruh Barat dan Timur itu berterima di bumi Indonesia. Dalam hal itu pula, Sanusi Pane telah bersikap mengambil jalan sintesis keduanya bagi Indonesia.
Kini, Indonesia tangguh; Indonesia tumbuh. Gema 76 tahun merdeka ini menguatkan kehendak mewujudkan mimpi kemajuan. Bahasa Indonesia juga dimajukan agar mencapai puncak status bahasa internasional, sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Pasal 44).
Tentu melalui pembibitan murni di bumi Indonesia, bahasa Indonesia tangguh; bahasa Indonesia tumbuh. Untuk menarasikan bahasa Indonesia yang demikian di dunia internasional, legenda Barus perlu dihidupkan kembali. Revitalisasi ini pun perlu kajian kebahasaan transdisipliner!
------------------------------------------------------------------------------
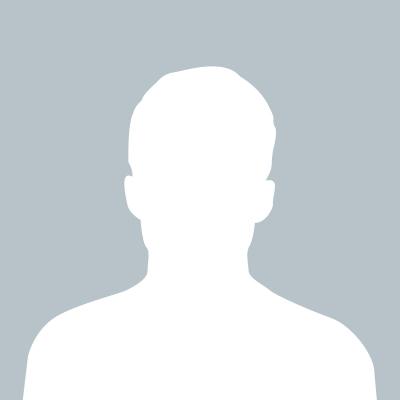
Maryanto
Maryanto, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara.
