Menggerakkan Bahasa Persatuan Indonesia: 76 Tahun Tangguh dan Tumbuh
Apa musabab Indonesia tetap tangguh dan tumbuh selama 76 tahun, padahal Indonesia kerap didera krisis? Krisis pandemi COVID-19 telah berlangsung dua tahun. Entah kapan krisis ini berakhir. Dari setiap krisis, terbukti Indonesia tangguh dengan tetap bergeraknya bahasa persatuan. Krisis demi krisis justru menumbuhkan optimisme. Indonesia tetaplah tumbuh menjadi negara dan bangsa yang maju.
Momentum76 tahun Indonesia merdeka pun menyegarkan ingatan publik pada sosok pemersatu, Josip Broz Tito, yang memperoleh gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Indonesia pada tahun 1958, yang sekarang tinggal kenangan. Cobalah tengok sejenak ke negara Yugoslavia yang dilahirkan Tito. Negaranya telah bubar jalan, terpecah belah. Untuk krisis 1998 di Indonesia, istilah ‘balkanisasi’ juga sempat terungkap oleh Lee Kuan Yew. Namun, dalam buku One Man’s View of the world (2013) istilah itu ditepis karena adanya warisan yang tak-ternilai, yakni bahasa persatuan Indonesia. Bahasa persatuan Indonesia tampak tangguh berwujud poros penggerak Pancasila.
Gerakan lahirnya persatuan
Sila ketiga (Pancasila) berisi teks bahasa yang berperan sebagai titik sentral cara pandang bersama untuk bergerak menjadi sesama Indonesia atas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (sila kedua). Pada dasarnya, setiap insan manusia Indonesia diharapkan dapat menjadi khalifah Tuhan di muka bumi, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (sila pertama). Tentu, harapan terakhir ialah terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (sila kelima) dengan jalan demokrasi sebagaimana rumusan sila keempat dalam teks Pancasila.
Persatuan Indonesia tentu tumbuh bergerak. “Bahasa Indonesia tidak [belum] ada,” kata M. Yamin yang dicatat oleh M. Tabrani dalam karya tulis otobiografi (Tabrani, 1978: 42--43). Kepada Yamin—yang sedang “naik pitam”—Tabrani menyatakan, “Kalau belum ada, harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia Pertama ini.” Begitulah pernyataan Tabrani yang memperoleh persetujuan Sanusi Pane pada tanggal 2 Mei 1926. Sebelum Sanusi hadir menyetujui pendapatnya, Tabrani mengaku kalah. Kekalahan ini berimplikasi pada pergerakan nasional yang nyaris gagal untuk melahirkan persatuan Indonesia.
Gerakan bahasa persatuan memang sempat terhenti; macet total dalam perdebatan sengit antara kubu Yamin dan kubu Tabrani. Perdebatan ibarat pertandingan sepakbola: sebelum turun minum, skornya 2-1 untuk kemenangan Yamin. “Djamaloedin condong pada pemikiran Yamin,” jelas Tabrani. Posisi skor berubah dari semula 2-1 menjadi skor 2-2. Skor berimbang. “Sebab Sanusi Pane menyetujui saya.” Demikian Tabrani menjelaskan. Dalam penjelasan itu Yamin sungguh-sungguh menindaklanjuti hasil semi-final tersebut.
Hasil finalnya adalah apa yang disampaikan oleh Yamin pada Kongres Pemuda Indonesia Kedua atas jasa Sugondo Joyopuspito selaku ketua. Tiga butir tentang tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan Indonesia merupakan hasil akhir dalam bentuk teks Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Catatan Tabrani itu sangat menarik. Istilah Sumpah Pemuda tidak pernah disebut-sebut sebelumnya. Ikrar Pemuda merupakan istilah usulan Yamin. Sementara itu, Sanusi mengusulkan istilah Kebulatan Tekad Pemuda.
Kepahlawanan Sanusi Pane
Tiga gerakan paripuna dilakukan Sanusi. Gerakan pertama tentu berupa tindakan kepahlawanan melahirkan bahasa persatuan Indonesia. Dalam Kongres Pemuda Indonesia Pertama pada tanggal 30 Mei hingga 2 Mei 1926, Sanusi berperan ganda: sebagai panitia kongres dan—sekaligus—sebagai perumus hasil kongres. Secara spesifik, karena adanya persetujuan Sanusi, gagasan bahasa persatuan Indonesia tersebut dapat dilanjutkan oleh Yamin ke dalam Kongres Pemuda Kedua pada tahun 1928.
Gerakan kedua adalah “gerakan sukma” dalam indah kata, menurut kritik sastra (Teeuw, 1994). Tak-pelak Sanusi merupakan tokoh penggerak sukma atau jiwa keindonesiaan. Sanusi bergerak; berjuang tidak melalui kekuatan senjata api, tetapi melalui keindahan kata-kata. Karya sastra perdananya berupa kumpulan sajak Pancaran Cinta (1926) dan disusul dengan Puspa Mega (1927) serta naskah drama Airlangga (1928). Masih banyak lainnya.
Sebagai tindak lanjut Kongres Pemuda Kedua (1928)—untuk menjunjung bahasa persatuan Indonesia—gerakan sukma juga ditempuh melalui penerbitan pers. Majalah Timboel semula terbit berbahasa Belanda, kemudian—oleh Sanusi, dengan keberaniannya—diubah beberapa halaman menjadi berbahasa Indonesia. Penerbitan majalah Pujangga Baru tidak terlepas dari Sanusi sebagai salah satu tokoh penggerak. Atas gerakannya juga, kantor berita Antara terbukti dapat berdiri hingga sekarang.
Keindahan kata-kata dalam perjuangan Sanusi terbaca pula dari terjemahan etnografik atas cerita Arjuna Wiwaha (karya Empu Kanwa pada abad XI). Teks gubahan cerita itu diperoleh pada tahun 1926 dalam tulisan beraksara Budha dan berbahasa Jawa Kuno (A’ang Pamudi Nugroho dkk., 23 Februari 2021). Saduran itu dicari teks awalnya untuk menjaga keindahan aslinya dalam bentuk puisi (kakawin). Dari teks Jawa Kuno itu, Sanusi adalah penerjemah pertama dalam bahasa Indonesia.
Gerakan ketiga merupakan kepahlawanan Sanusi dalam pelembagaan bahasa persatuan Indonesia. Sanusi sangat cerdas. Bahkan, Ichwan Azhari (23 Februari 2021) mencatatnya sebagai orang yang paling jenius. Sanusi mampu mengonstruksi memori Indonesia agar melembaga sebagai komunitas yang dibayangkan (imaged community dalam istilah Benedict Anderson, 2006), antara lain dengan mengambil cerita Jawa kuno itu. Dari sumber Jawa kuno, pengembangan bahasa Indonesia dimulai.
Untuk mengembangkan bahasa Indonesia, menurut Sanusi dalam koran Pemandangan (2—6/4/1940 dalam catatan Priyantono Oemar, 23 Februari 2021), perlu dukungan budaya yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Kebudayaan baru harus berdasarkan humanisme Timur. Namun, Sanusi juga tidak menampik pentingnya humanisme Barat. Garis tengah sebagai sintesis antara Barat dan Timur itu dipilih melalui tokoh Barat yang diwakili oleh Faust dan tokoh Timur dalam semangat patriotik dari pribadi tokoh Arjuna tersebut.
Pentingnya kelembagaan bahasa persatuan Indonesia merupakan usulan yang diputuskan dalam Kongres Bahasa Indonesia Pertama (Solo, 1938). Sebagai tindak lanjut, dibentuklah komisi pendirian “Instituut Bahasa Indonesia” yang digagas oleh Sanusi. Gagasan besar itu pun masih diperlukan hingga sekarang bermaujud lembaga kebahasaan, antara lain: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara.
Sikap patriotik Sanusi Pane—pejuang dari Sumatera Utara—agaknya perlu hadir memupuk dan menumbuhkan semangat juang pada generasi pelapis. Dengan menggerakkan bahasa persatuan Indonesia, Sanusi bekerja paripurna dan tulus serta tanpa pamrih untuk beroleh penghargaan dari negara. Peninggalannya adalah sifat nasionalisme, kepahlawanan, dan patriotisme bagi generasi kekinian.
Untuk tetap tangguh dan tumbuh, tidakkah Indonesia kini perlu patriot sejati? Bertanyalah pada saat krisis seperti ini. ---
*Penulis adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara.
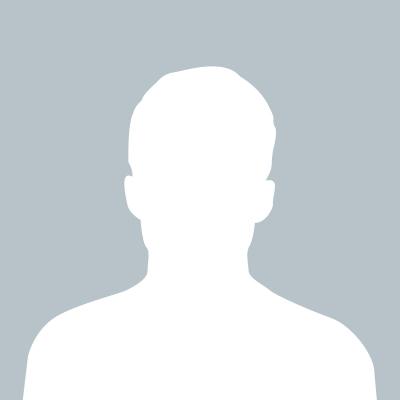
Maryanto
...
