Miskonsepsi Gerakan Literasi di Sekolah
Secara etimologis, literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus yang artinya ‘melek huruf’.
Pada taraf ini, tahu mengeja berarti sudah literat. Namun, literasi tidak
sebatas memahami huruf. Dalam semiotika, huruf adalah simbol. Sebagai simbol,
bahan bacaan tidak terbatas pada huruf saja. Pada masa purbakala, leluhur kita
membuat banyak simbol di dinding-dinding gua. Mereka memahami simbol-simbol itu
dengan baik.
Saat ini
simbol-simbol visual tidak lagi hanya ada di gua-gua. Simbol-simbol itu hadir
dalam grafis, peta, ilustrasi, poster, dan sebagainya. Jika tak paham simbol-simbol
itu, sesungguhnya kita juga tidak literat. Selain itu, leluhur kita mampu
membaca tanda-tanda alam sehingga bisa membuat keputusan dengan baik tentang waktu
berburu, menanam, dan melaut. Mereka mempelajari rasi bintang sebagai navigasi,
lalu membuat keputusan.
Saat ini
tanda-tanda alam sudah berserak. Dari tanda-tanda itu kita belajar membuat
keputusan. Namun, jika tanda-tanda itu sebagai gejala tidak membuat kita
terampil dalam membuat keputusan, kita juga sebenarnya tidak literat. Artinya,
literat tidak sebatas mengeja huruf. Literat berarti harus mampu membuat
keputusan logis dari berbagai premis sebagai simbol yang dikomunikasikan. Dalam
hal ini, berliterasi berarti bernalar kritis.
Kesadaran Berpikir
Jika gerakan
literasi di sekolah tak mampu membuat siswa untuk berpikir kritis sehingga berhenti
hanya sebatas membaca, apalagi mengeja, sesungguhnya gerakan literasi tersebut
sudah salah kaprah. Itu karena berliterasi tak terbatas pada kegiatan membaca,
apalagi 15 menit sebelum belajar. Literasi sesungguhnya mencakup keterampilan
mendengar, berbicara, membaca, dan menulis (Kennedy, 2012: 41). Walau begitu, semua
keterampilan itu harus mengandung kesadaran berpikir dari siswa. Itu karena
inti dari gerakan literasi adalah kemauan untuk berpikir kritis.
Karena ketiadaan berpikir itulah kiranya
mengapa pada periode kontemporer, peringkat literasi generasi muda kita sangat
mengkhawatirkan. Ada anggapan bahwa rendahnya peringkat literasi itu karena
budaya kita cenderung lisan. Namun, anggapan itu tak sepenuhnya benar, bahkan
justru salah. Buktinya adalah dengan tradisi lisan pada masa kuno, kita pernah
berhasil membuat Candi Borobudur dan memiliki budaya maritim yang tangguh.
Artinya, tradisi lisan tak menjadi penghalang bagi berkembangnya budaya
literasi. Berbicara dan membaca sesungguhnya saling berhubungan, begitu juga
dengan keterampilan mendengar dan menulis. Satu dengan lainnya saling terkait
dan tak dapat dipisahkan (Guzzetti, 2002: 278).
Berbagai
penelitian telah menunjukkan bahwa berbahasa lisan ternyata turut melengkapi
pengalaman literasi. Tidak hanya Indonesia, bangsa Yunani dan Romawi juga
cenderung bertradisi oral atau
lisan (Al Alusi: 38—48). Artinya, tak sepenuhnya lagi kita pasrah pada anggapan
bahwa muasal dari rendahnya peringkat literasi kita adalah sebagai dampak dari
tradisi lisan. Kalau selalu begitu, kita hanya mencari alasan, bukan menggali
jawaban bagaimana meningkatkan prestasi.
Relasi antara
tradisi lisan dan literasi sangat kompleks dan harus dipandang secara
komprehensif (Harris, 1991; Thomas, 1992; Ong, 2002). Lagi pula, secara alami
manusia berkembang dari budaya lisan. Sejarah selalu diawali dari kisah
prasejarah. Itu artinya bahwa pengetahuan mendalam awal murid berasal dari
proses belajar dari bahasa lisan (Ray dan Medwell, 1991: 70—71). Jadi, sekali
lagi, adalah keliru memasrahkan diri bahwa rendahnya literasi kita adalah
produk dari kebiasaan lisan leluhur.
Kelisanan dan
literasi bukanlah sebuah kontinum yang linear seolah bahwa jika masih
bertradisi lisan, berarti tak akan literat. Atau dengan mengutip Dewayani,
seolah jika sebuah bangsa sudah literat, mereka akan meninggalkan budaya lisan
(2017: 16). Justru, budaya lisan melalui kebiasaan bercerita dan mendongeng
harus dikukuhkan kembali. Saya malah berpikir bahwa rendahnya peringkat literasi
kita adalah dampak dari minimnya budaya mendongeng oleh orang tua di rumah.
Kita tidak lagi
kuat di dasar sehingga rapuh di ujung. Supaya cepat matang, kita mengarbit
anak. Masa mudanya untuk bermain dipangkas dan dibuang karena merasa bahwa bermain
adalah ancaman bagi tumbuh kembang anak kecil. Padahal, ketika anak bermain,
sesungguhnya mereka sedang belajar. Ironisnya, cara belajar dengan bermain itu
dihilangkan. Saat ini, bahkan ketika PAUD, anak sudah dipaksa untuk bisa baca,
tulis, dan hitung (calistung). Anak menjadi depresi.
Mereka yang
sewajarnya menerima dongeng dari orang tuanya malah harus menerima angka dan
huruf. Bahwa pada usia dini anak sudah bisa calistung bukan menjadi pembenaran.
Bahkan, monyet juga bisa dilatih untuk bisa bersirkus di atas sepeda-sepedaan
serta anggun memakai payung. Namun, itu semua semu belaka. Manakala hujan
turun, sang monyet pasti akan berlari dan membuang payung itu.
Artinya, monyet
terlihat pintar, tetapi sejujurnya ia kosong. Begitu juga dengan anak kita.
Mungkin ia terlihat pintar karena sudah bisa calistung, tetapi sejujurnya ia
rapuh karena fondasinya dipangkas. Percaya atau tidak, manusia belajar secara
alami. Ketika bayi melihat tangan kita menjentik lebih dari biasanya, ia
terperangah. Sesungguhnya ia sedang belajar matematika dasar sehingga keheranan,
mengapa jentikan kali ini lebih banyak?
Nol Besar
Ketika pertama
kali tumbuh dalam bentuk janin hingga berusia dua tahun, anak sejatinya sudah
belajar literasi dasar (Hoe dan Golant, 1985). Ketika anak membagi kue dengan
rata, ia sudah belajar bilangan pecahan (numerasi). Gerakan literasi yang kini
diajarkan di sekolah sebetulnya hanya pengayaan. Namun, pengayaan itu terkesan
jadi pemiskinan daya berpikir. Gerakan literasi, misalnya, justru dipisahkan
dengan numerasi.
Padahal,
definisi teranyar tentang literasi sudah meluas hingga ke ranah digital.
Sesuatu yang bijak memang jika membudayakan literasi di sekolah. Namun, gerakan
itu kini seperti seekor monyet dengan payungnya. Maaf, ini hanya ilustrasi.
Kini, baik pawang monyet (guru) maupun monyet (siswa) itu sama-sama tak
mengetahui makna di balik gerakan literasi. Gerakan literasi cenderung dipandang
sebagai kosmetika belaka.
Maka, dibuatlah
mading mewah, pohon, hingga gerobak literasi. Gerakan literasi akhirnya tidak
saja sudah lari dari konsep, tetapi juga dari pengertian mendasarnya. Semula
siswa sangat antusias dengan gerakan literasi. Mungkin mereka menduga bahwa ini
akan menjadi asupan baru setelah budaya bercerita dari rumah hilang tenggelam.
Namun, gerakan literasi itu kering. Siswa hanya diberi kesempatan untuk membaca
buku apa saja tanpa komando.
Betapa tidak? Sekolah tidak memfasilitasi gerakan
berpikir dan berdialektika yang berdenyut di ruang-ruang kelas. Sebagai
dampaknya, lama-lama kini gerakan membaca itu sudah hilang dari sekolah. Gerakan
literasi hanya menjadi bisnis baru berupa webinar para cendekiawan di
ruang-ruang digital. Gerakan literasi ini, maaf untuk berkata jujur, adalah nol
besar belaka. Kita pun kembali berkata, “Ini semua karena budaya lisan leluhur.”
Oh!
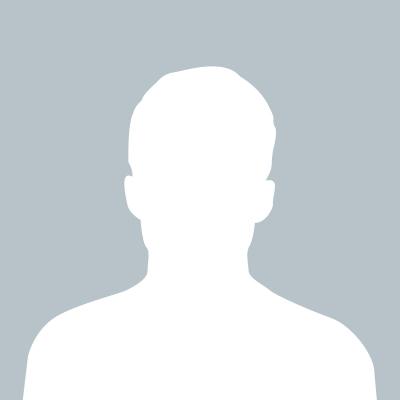
Riduan Situmorang
Penulis adalah guru bahasa Indonesia SMAN 1 Doloksanggul-Humbang Hasundutan, instruktur sastra gigital tingkat nasional, aktif berkesenian di Pusat Latihan Opera Batak (PLOt) Medan dan Toba Writers Forum (TWF).
