Pluralisme Sastra
Keberagaman dalam berekspresi adalah jembatan untuk
menyatukan wujud nilai perbedaan. Namun, tidak jarang
pula hal itu menjadi potensi timbulnya konflik karena tidak dibangun
dan didasari prinsip humanisme
(kemanusiaan). Latar belakang ego yang sempit serta perkembangan dimensi sosial
yang penuh dinamika melahirkan pelbagai perbedaan.
Sastra sebagai bagian dari kelenturan budaya seyogianya menjadi jalan atau media dalam mencapai tujuan
prinsip-prinsip humanisme. Akar
budaya yang tertanam puluhan abad silam merupakan dimensi egaliter (kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diberlakukan
sama) demi tujuan mematangkan semarak kehidupan sastra.
Dalam referensi harfiah, tentu kita cukup memahami makna pluralisme dalam
sastra. Dalam perjalanannya, sastra memunculkan berbagai aliran, seperti idealisme, materialisme, dan eksistensialisme.
Dalam kamus umum, ragam sastra sering disebut sebagai genre sastra. Objek sastra memiliki dimensi ruang yang tidak
terbatas, hingga menjadi subjek pembahasan yang tidak mengenal waktu. Mungkin
dengan cara dan gaya yang berbeda, penulis meyakini begitu banyak penulis lain
yang menulis tentang hal tersebut.
Pada sisi ini, penulis ingin mengejawantahkan makna
sastra yang tidak terikat pada aturan teori. Selama ini kita sering terjebak dan terkungkung dalam subjektivitas
pemikiran. Tanpa sadar kita telah membelenggu, bahkan memenjarakan objektivitas
pemikiran dinamis. Lalu, apakah ada penyair atau sastrawan yang terlahir dalam
kebesaran sastra, tetapi harus terikat oleh sebuah aturan yang normatif? Esensi nilai
sastra tidak harus dibatasi pada sebuah sublimasi atau metafora aksara sehingga
mematikan dalil kreativitas pemikiran positif.
Kita tentu tidak menampik kritik yang sifatnya perbaikan. Namun, sejauh mana
kritikan itu bisa memberi nilai ukur (kualitas) pada karya-karya sastra yang
dihasilkan? Bagaimanapun, karya-karya
sastra yang bagus dan berkualitas harus melalui proses seleksi alam. Harus kita
akui bahwa banyak pegiat sastra yang mengelak dan menghindari proses itu
karena kehidupan sastra kini berada di
dimensi ruang yang sangat
dekat dengan pembaca.
Ketika beberapa abad silam seorang penyair besar Eropa, Johann Wolfgang von Goethe, terlahir dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu,
dunia sastra Barat seolah-olah seperti tidak tertandingi. Mahakarya besar lahir sehingga
sastra Barat dianggap sebagai simbol dari segala peradaban sastra. Goethe
tidak hanya merupakan sastrawan, tetapi juga merupakan tokoh filsafat pada masa itu.
Revolusi sastra Barat dianggap sebagai karya absolut
sehingga tak pernah terpikirkan bahwa sastra Timur juga mempunyai daya religius yang sangat tinggi dan menawan. Namun, sastra Timur tak mampu dibandingkan dengan sastra Barat dalam pergulatan eksotisme dan subjektivitas Barat. Kemudian, muncul sastrawan-sastrawan
sufi yang berpegang pada esensi religiositas karya, terutama di Jazirah Arab.
Jika dilihat perbedaan sastra antara Barat dan Timur, memang bukanlah sebuah kultus yang harus
diperbandingkan. Namun, karena dimensi
seni berkembang juga seperti halnya ilmu pengetahuan, hal
itu membuka ruang wawasan baru hingga akhirnya pada satu masa, sastra Barat menjadi membosankan dan penuh daya tipu muslihat. Goethe pun membaca situasi itu, kemudian menjadi tertarik untuk mendalami sastra Timur yang telah melahirkan sastrawan terkenal, seperti Attar, Iqbal, dan Rumi.
Dalam beberapa perbandingan, sastra adalah ilmu tanpa
wujud yang mendeklarasikan topik pemikiran sastrawan hingga melahirkan sebuah
nilai dan ilmu. Catatan karya sastrawan Barat dan Timur di atas bisa kita ambil secara
sederhana dalam perbandingan keberagaman genre sastra.
Dengan demikian, konsep pluralisme juga terjadi dalam catatan perjalanan sastra. Namun, sayangnya pada
masa kini kebanyakan pegiat sastra mematangkan pengakuan dirinya sebagai
seorang sastrawan ataupun penyair dari sebuah proses instan,
tanpa melewati sebuah proses
seleksi alam yang terukur (terdapat parameter). Itu sangat sulit
karena nyatanya sampai saat ini kita belum mampu
menjadikan sastra sebagai sebuah industri
sehingga tidak ada nilai ukur
(parameter) yang jelas.
Tanpa disadari, seiring perubahan zaman yang berorientasi pada
pemikiran-pemikiran bebas, tempat dimensi kontemplasi telah memberikan
kebebasan kepada orang per
orang, orientalis sastra sangat banyak dipengaruhi oleh
berbagai aliran yang individualis. Konteks sintaksis dan morfologis
diperlunak dengan pemahaman individu. Karena
itu, tidak heran jika saat ini bermunculan karya-karya sastra
yang dikatakan sebagai karya absurd (tidak masuk akal). Karya-karya sastra
pun menjadi uji coba para sastrawan untuk mencari jati diri yang baru meski harus menabrak prinsip-prinsip dasar teori sastra.
Jika sebelumnya diambil contoh karya Johann Wolfgang von Goethe, hal
itu hanya untuk menggarisbawahi titik masa yang kini tentunya
sudah tidak relevan. Hanya saja, ikatan emosional yang menjiwai karya-karyanya telah
menanamkan makna-makna filosofi yang terus dipakai sampai saat
ini. Tentu akan berbeda perbandingannya jika kita menyamakannya dengan Chairil
Anwar, misalnya. Sastra itu merupakan sebuah karya yang dinamis. Artinya, terdapat polarisasi
pemikiran dan masa yang dilewati oleh para sastrawan.
Ada
yang harus kita cermati dalam perubahan sosial
sebagai akibat perubahan
masa yang terus bergerak sesuai dengan dinamika zaman. Ini adalah masa saat teknologi berkembang begitu pesat
dan sangat masif sehingga terjadi
pergeseran tekstur sosial. Hal itu mengakibatkan rendahnya literasi dan kerancuan
penggunaan bahasa baku. Bahasa
yang diserap oleh penulis dan pegiat sastra banyak termanipulasi oleh informasi
bahasa yang salah. Sebagian lapisan pembaca terlalu bergantung pada penulisan
frasa yang didapatkan dari media berbasis daring.
Munculnya paradigma baru dalam eksodus sastra
(meninggalkan tempat asal secara
besar-besaran) mengarahkan pada bentuk dan aliran sastra baru. Itu karena
perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat
secara tidak sadar menyemarakkan kehidupan sastra
serta turut berperan di dalamnya meski dengan alasan agar hal
itu tetap bisa menghasilkan dan
mempertahankan karya-karya sastra.
Bagi sebagian penulis sastra pun, terutama bagi para
pemula, tidak begitu sulit untuk bersaing dalam proses seleksi alam
untuk menghasilkan karya objektif. Di
satu sisi, peran kritik sastra tidak mampu mengimbangi kesalahan-kesalahan
dasar penulis karena begitu banyaknya media berbasis daring.
Seyogianya, meski sastra berkembang tanpa batas karena dinamika
teknologi dan pikiran, bukan berarti hal itu meninggalkan konsep dasar tentang literasi dan kebahasaan. Pluralisme sastra yang berkembang begitu pesat
seharusnya tidak meninggalkan beberapa aspek yang menjadi nilai kesatuan dalam
kerangka kebangsaan, yakni budaya dan estetika bahasa. Untuk
itu, mungkin perlu ada sebuah regulasi (aturan) yang mengatur kedudukan
dan tujuan sastra secara nasional.
Dalam beberapa sudut pandang dan dari catatan sejarah
sastra yang panjang di negeri kita, sudah sewajarnya kita sangat mengapresiasi munculnya
seniman-seniman sastra hebat antargenerasi. Pluralisme terjadi karena adanya pembacaan
dinamika zaman yang berbeda. Untuk itu, kita bisa berbangga dengan beberapa
sastrawan besar, seperti Sapardi Djoko Damono, Umbu Landu Paranggi, Budi Darma,
Calzoum Bachri Soetardji, dan Pramoedya Ananta Toer.
Artinya, pluralisme sastra berdampak pada perubahan genre yang saling melengkapi sesuai dengan ukuran waktu yang bergulir. Karena itu, kematangan karya sastra tidak hanya diukur dengan kecepatan pembaca untuk menjangkau karya sastra melalui dimensi media yang berbasis teknologi digital. Ada proses yang harus dilewati meski begitu naif kalau dikatakan bahwa terjadi pembiasan yang membatasi ruang kreatif antara senior dan junior. Dimensi sastra pada dasarnya tidak menganut pembatasan usia seorang seniman sastra, tetapi lebih berpijak pada kualitas dan konsistensi karya yang dihasilkan seseorang.
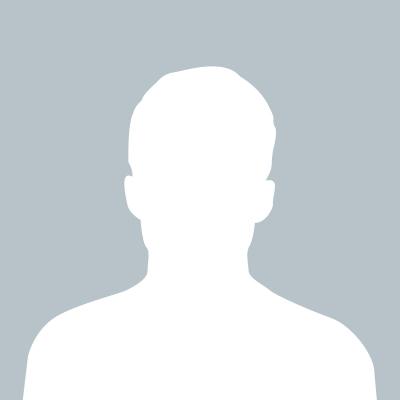
Vito Prasetyo
Penulis adalah pegiat sastra dan peminat bahasa.
