Perspektif Cerdas Membangun Keberagaman lewat Gerakan Literasi
Tekstur Sosial
Dalam memahami esensi permasalahan sosial, terutama
yang berorientasi kebangsaan, sudah
selayaknya kita menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dari keberagaman
sosial. Perbedaan latar belakang yang mencakup suku, ras, etnis, budaya,
pendidikan, agama, serta sosial-ekonomi tentu sangat rentan memunculkan sikap-sikap
apriori. Namun, dalam tatanan Pancasila, persepsi itu adalah sebuah dimensi
penguatan untuk melepaskan ikatan budaya primordial.
Pancasila adalah kesatuan yang bersifat universal. Artinya,
lingkup kebangsaan yang berwawasan Pancasila tidak mengenal kasta atau
tingkatan masyarakat meskipun dalam struktur budaya, Indonesia memiliki ratusan
suku dan subsuku daerah. Begitu juga jika ditinjau dari bahasa lokal/daerah,
jumlahnya sangat banyak. Bahasa dan budaya daerah tidak terlepas dari riwayat
sejarah berdirinya bangsa ini. Sejak masa kerajaan di wilayah Nusantara hingga
masa kini, struktur bahasa dan budaya menjadi konsep desain bagi kelangsungan bangsa.
Setiap masa tentu mempunyai tantangan tersendiri, mulai
dari masa penjajahan, kemerdekaan, hingga modern. Kita meyakini bahwa sebuah
bangsa dalam melewati sebuah masa tentu melalui proses panjang yang tiap-tiapnya
mempunyai dinamika dan tantangannya sendiri.
Tantangan yang saat ini dianggap jauh lebih berat
adalah makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam resultan sosial akan tumbuh
perilaku-perilaku baru yang dapat berdampak terhadap atau berpotensi menimbulkan
perubahan ekosistem kehidupan serta pergeseran struktur bahasa dan budaya.
Apakah itu bisa kita sebut sebagai sebuah revolusi sosial?
Teori terkait dengan hal itu dikemukakan oleh seorang sosiolog
Amerika, Kingsley Davis.
Menurutnya, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur
dan fungsi masyarakat. Hal itu senada dengan teori dari tokoh pendidikan
Indonesia, Prof. Dr. Selo Soemardjan, yaitu perubahan sosial meliputi segala
perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi
sistem sosialnya dan di dalamnya tercakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku
antarkelompok dalam masyarakat.
Sebagai sebuah simpulan, perubahan sosial mengikat
masyarakat dengan peristiwa sosial yang menyangkut masa lalu. Dalam memecahkan
perubahan sosial yang terjadi, dibedakan beberapa teori, yakni teori evolusi,
teori konflik, teori fungsional, teori siklus, dan teori pembangunan. Di samping
itu, waktu menjadi sebuah fase dan alat dalam merumuskan perubahan-perubahan tersebut.
Perspektif Literasi
Sebuah skeptisisme yang kadang terjadi dalam
masyarakat adalah pembiaran
dalam merawat sumber-sumber literasi akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan
masanya. Sementara itu, tantangan yang dihadapi kian besar dampaknya,
terutama bahasa ibu di beberapa daerah makin tergerus, bahkan nyaris punah.
Mungkin itu terjadi karena adanya anggapan bahwa literasi berbasis daerah,
seperti bahasa ibu, sudah ketinggalan zaman atau karena akses untuk mendapatkan
sumber literasi makin instan dengan alat bantu teknologi, seperti gawai.
Lebih lanjut, dalam mengaktualisasikan gerakan
literasi, ada baiknya kita mengenal apa yang dimaksud dengan literasi.
Literasi termasuk dalam kelas nomina atau kata benda. Istilah literasi secara
etimologis berasal dari bahasa Latin—literatus—yang berarti ‘orang yang
belajar’. Dalam bahasa Latin juga ditemukan littera,
yaitu ‘huruf’.
Sementara itu, istilah literasi dalam bahasa Indonesia
merupakan serapan dari kata bahasa Inggris, yaitu literacy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
literasi adalah ‘kemampuan menulis dan membaca’. Literasi begitu kuat dan
sangat erat dengan proses membaca dan menulis.
Namun, makna literasi sebenarnya memiliki pemahaman
yang lebih kompleks dan dinamis. Artinya, itu tidak hanya terbatas pada kemampuan
membaca dan menulis, tetapi juga pada kemampuan mengolah, menganalisis, dan
memahami informasi dari bacaan serta mampu mengomunikasikannya kembali melalui
tulisan.
Dalam praktik sehari-hari, persoalan dan pembahasan
literasi sangat erat kaitannya dengan proses belajar-mengajar. Maka, tidak bisa
dimungkiri bahwa seorang pendidik atau guru mempunyai tanggung jawab langsung terhadap
pendidikan formal. Oleh karena itu, pendidik atau guru harus mempunyai
kemampuan dalam mencari, menemukan, serta menentukan sumber informasi yang
sesuai dengan kebutuhan pengajaran. Itulah yang disebut dengan kemampuan
literasi. Namun, apakah gerakan literasi itu hanya menjadi tanggung jawab
pendidik atau guru?
Untuk menjawab pertanyaan itu, tentunya harus ada
perspektif yang luas. Di tengah dinamika zaman yang kini disebut sebagai era
digital atau ada yang menyebutnya sebagai postmodern,
pemahaman tentang literasi tentu juga berkembang pesat sesuai dengan tantangannya.
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi
informasi, membuat pemahaman kemampuan literasi tidak hanya terbatas pada
membaca, menulis, dan berhitung.
Dengan mengutip Harvey J. Graff (sejarawan komparatif
sosial) dalam buku The Legacies of
Literacy, kemampuan dasar literasi (membaca, menulis, dan berhitung) dapat mewujudkan
kreativitas, inovasi, dan inspirasi. Hal itulah yang kemudian kita baca sebagai
konsep atau desain edukasi di Indonesia, yaitu menumbuhkan kemampuan peserta
didik untuk berinteraksi sosial, tidak hanya di dalam pendidikan formal, tetapi
juga di lingkungan yang mengandalkan penguasaan teknologi digital sederhana,
seperti gawai.
Persoalannya adalah literasi digital rentan menimbulkan
keberagaman persepsi. Itu terjadi karena peserta didik memiliki keterbatasan waktu
untuk menulis. Sementara itu, pengertian literasi itu adalah satu kesatuan.
Dilema itu tentunya bukan merupakan persoalan kompleks karena skema pendidikan
mampu menjangkau keterbatasan peserta didik dengan literasi digital yang lebih
sederhana, tetapi sangat praktis. Selain itu, inovasi pemikiran peserta didik
lebih terlatih untuk menangkap materi secara cepat.
Mungkin perlu juga untuk dikaji lebih mendalam
persoalan indikator (nilai ukur) bagi peserta didik dalam menguasai literasi yang
terkait dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Selain itu,
perlu dikaji sejauh mana tingkat keberhasilannya dengan Uji Kemahiran Berbahasa
Indonesia (UKBI) sebab ada paradigma dalam masyarakat saat ini bahwa makin
majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berimbas pada pergeseran
nilai-nilai sosial, termasuk etika budaya dan bahasa.
Seperti halnya sebuah peribahasa, “Banyak jalan menuju
ke Roma”, yang harus dipahami adalah
bagaimana memecahkan akar sebuah masalah. Apakah penerapan sistematika teoretis
sudah sejalan dengan perkembangan zaman ataukah perangkat sistem kita belum
mampu mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)? Tentunya
banyak cara yang bisa ditempuh. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan
fungsi literasi yang perannya sangat vital dalam memahami konsep informatika
melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dari uraian di atas, dalam penajaman aspek keberagaman
dan gerakan literasi, sejauh ini pemerintah telah memediasi bahkan mendorong
dalam menjaga tekstur literasi dan nilai-nilai budaya lokal, seperti makin
banyaknya komunitas atau kelompok pegiat literasi. Bahkan, secara kelembagaan, semua
daerah diperkuat dengan adanya balai/kantor bahasa. Tentu itu sangat
menggembirakan untuk menggalakkan program pengembangan literasi.
Melalui penguasaan nilai-nilai seperti termaktub dalam
butir-butir Pancasila, keberagaman menjadi unsur-unsur dasar untuk merekatkan
kebinekaan bangsa. Harus kita sadari bahwa dalam fase transisi sosial, perspektif (sudut pandang) tentang
literasi tidak hanya mencakup ekosistem bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai
humanisme (kemanusiaan). Oleh
karena itu, kita membutuhkan pemikiran-pemikiran masa lampau yang mampu
mereduksi perubahan zaman, seperti pemikiran cerdas seorang Soedjatmoko.
Terkait dengan Soedjatmoko, karya-karyanya telah
dialihbahasakan ke dalam beberapa bahasa, seperti bahasa Inggris dan bahasa Jepang.
Jika kita menyelami pemikirannya yang disajikan seakan tersirat, literasi
sangat penting perannya. Sementara itu, semasa hidupnya, modernisasi teknologi
masih belum begitu maju, termasuk teknologi digital yang masih sangat terbatas.
Namun, pemikiran Soedjatmoko seakan sudah menjangkau masa yang lebih luas. Soedjatmoko
bahkan menyebut dirinya sebagai independent
thinker (pemikir yang berdikari).
Nah, bagaimana persoalan lintas masa yang kita hadapi
sekarang? Tentu hal itu begitu kompleks dengan munculnya banyak keberagaman.
Sebagai individu, manusia tidak akan bisa melepaskan diri dari faktor-faktor entitas (wujud) manusia sebagai
makhluk sosial. Maka, esensi dasar yang harus dipahami adalah membangun
nilai-nilai humanisme (kemanusiaan) dengan akal sehat. Siapa pun manusia,
prinsip dasarnya adalah mampu berinteraksi sosial dengan menggunakan literasi
atau bahasa.
Jika kita kembali pada terjadinya perubahan sosial,
yang kadang diterjemahkan lebih ekstrem dengan revolusi sosial, tentunya hal
itu juga berimbas pada metode penguasaan dan pemahaman literasi. Dari jenisnya,
literasi kemudian bercabang dan berkembang, tidak hanya sebatas literasi
konvensional. Namun, kini juga ada yang disebut sebagai literasi digital. Kemudian,
literasi digital banyak digunakan karena pertimbangan kecepatan dan keakuratan
informasi.
Sebagai wawasan dalam memahami literasi, terutama literasi berbasis digital, di sini dapat kita lihat bentuk-bentuk digitalisasi sesuai dengan jenisnya. Sebagaimana referensi yang disadur dari Balai Pustaka, kompetensi digital terdiri atas
- Digital skill yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari;
- Digital culture
yang merupakan bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap
memiliki wawasan kebangsaan serta nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan;
- Digital ethics
yang merupakan kemampuan menyadari, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata
kelola etika digital (netiquette)
dalam kehidupan sehari-hari; dan
- Digital safety
yang merupakan kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, serta meningkatkan
kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital.
Dalam pengembangan dan pemanfaatan bentuk-bentuk
informasi melalui digital, seyogianya dasar-dasar pemahaman tentang literasi
harus terukur. Untuk itu, dijelaskan pada paragraf di atas bahwa literasi itu
tidak hanya meliputi pemahaman tentang menulis, membaca, dan menghitung, tetapi
juga pemahaman yang jauh lebih kompleks karena adanya dinamika teknologi dan nilai
ukur yang jelas.
Dalam perspektif keberagaman pembangunan gerakan
literasi, kita juga harus objektif bahwasanya unsur lokalitas harus didasari
oleh kearifan lokal. Itu karena banyak peninggalan sejarah menggunakan literasi
daerah yang nasibnya kini terpinggirkan. Pada posisi ini, pemerintah melalui Badan
Bahasa atau balai/kantor bahasa yang ada di daerah tentunya lebih mengedepankan
program-program dengan visi berbasis daerah masing-masing. Di sisi lain,
pemahaman literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab formal, tetapi potensi
adat juga turut berperan.
Penyerapan literasi yang berlatar belakang kultur
asing melalui sarana teknologi digital seharusnya memberikan nilai positif
dalam perkembangan literasi kita. Harus kita akui bahwa mencapai standar baku
memang bukan hal yang mudah. Di satu sisi, di Indonesia masih minim pakar
pedagogi yang secara khusus mendalami linguistik. Logikanya adalah kebutuhan itu
harus berbanding lurus dengan kemajuan teknologi digital karena peningkatan
kompetensi di bidang literasi memunculkan kemajuan ilmu pengetahuan yang
berbeda dengan kondisi sebelum modernisasi teknologi.
Ada yang menarik ketika Dr. Jatu Kaannaha Putri, M.A.
menulis artikel dan mengulasnya di laman Badan Bahasa, Kemendikbudristek,
beberapa waktu lalu dengan judul “Instagram sebagai Media Pembelajaran Bahasa
Indonesia dan Sastra”. Bagaimana menggagas perkembangan era digital pada
situasi yang dihadapi dalam segmen kehidupan saat ini? Begitu masif penetrasi
media sosial di pelbagai aspek kehidupan. Seperti yang kita ketahui, bahasa dan
sastra Indonesia sangat erat ikatannya dengan peran literasi.
Selain itu, ada yang menarik ketika wawasan itu dibuka
dengan pemahaman luas, seakan ruang atau dimensi baru terbuka. Media massa
tidak lagi menjadi objek pasif, tetapi juga dapat berperan sebagai produsen
informasi bagi khalayak atau masyarakat umum. Artinya, masyarakat diajak untuk
memerdekakan pola pikir (mindset) dari
sebuah konsep subjektivitas. Tinggal diubah bagaimana melihat perubahan ini
menjadi pola pemikiran dengan dimensi ruang digital (modernisasi teknologi).
Perubahan pola komunikasi yang terjadi, yaitu dari
konvensional ke digital, tentunya membawa dampak sebab-akibat. Kita dapat melihat
pola desain pembelajaran yang tidak lagi apriori pada kemajuan teknologi. Itu sangat
jauh berbeda dengan pola pembelajaran konvensional beberapa dekade lalu. Tentu
menjadi unik jika media sosial dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Hal itu
menjadi salah satu solusi cerdas untuk mengatasi keterbatasan yang dialami masyarakat
umum, terutama dalam gerakan menggiatkan literasi.
Jika sebelumnya kita menyinggung bahasa dan sastra Indonesia
sebagai wadah pengembangan literasi, tentunya tidak menutup kemungkinan bagi
keterbukaan inovasi dalam mengoptimalkan sumber-sumber literasi lainnya. Dalam
konsep pembelajaran, terutama bagi peserta didik, diharapkan potensi literasi dapat
digali dan didalami sebagai wawasan positif dalam memajukan iptek. Perlu
diingat pula bahwa literasi itu bukan sekadar pengetahuan tentang cara membaca yang
benar, melainkan juga tentang cara menulis yang benar.
Di sisi lain, sastra yang juga menjadi wadah
pengembangan literasi diharapkan mampu tumbuh dan berkembang di masyarakat
sebagai sebuah gerakan moral untuk menjaga nilai-nilai etika dan estetika. Selain
itu, patut disadari bahwa karya sastra harus mampu menyajikan cermin atau
potret masyarakat yang akhirnya menjadi wadah untuk membentuk karakter atau
perilaku positif dalam mempertahankan dan memajukan nilai-nilai literasi.
Akhirnya, menjadi sebuah harapan bahwa bahasa dan
sastra daerah juga merupakan gerakan literasi dari keberagaman struktur adat-istiadat
yang ada di Indonesia. Itu menjadi potensi ketahanan bangsa dalam menjaga serta
merawat nilai-nilai bahasa dan budaya yang di menjadi sumber dan referensi
literasi. ***
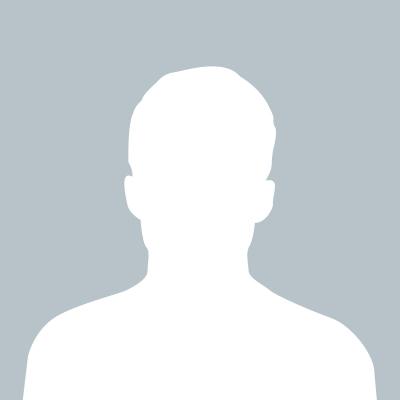
Vito Prasetyo
Penulis adalah sastrawan dan peminat bahasa
