UKBI untuk Martabat Bahasa
Sebagai bahasa resmi dan bahasa negara, bahasa
Indonesia semestinya dibuat bermartabat. Arti bermartabat tentu tidak lagi
sebatas bahasa utama dalam percakapan atau tulisan. Lebih detail, bahasa
Indonesia harus naik levelnya menjadi simbol profesionalisme sebagaimana bahasa
resmi sebuah negara, apalagi untuk berbagai bidang studi, di negara kita hasil
TOEFL menjadi syarat yang tak bisa ditawar sebagai bentuk profesionalisme. Pada
rekrutmen CPNS, beberapa bidang pekerjaan bahkan sudah mewajibkan TOEFL.
Artinya, di negara kita TOEFL sudah dibuat sebagai catatan administratif untuk profesionalisme.
Sesungguhnya,
negara lain juga sudah melakukan pemartabatan bahasa negara masing-masing. Oleh
karena itu, tentu saja memartabatkan bahasa Indonesia di tanahnya sendiri menjadi
tugas kita, apalagi saat ini kita sudah punya alat yang identik dengan TOEFL,
yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Sayangnya, UKBI (luring dan
daring) masih belum dipandang. Padahal, metode UKBI sudah sangat berkembang.
Saat ini sistem UKBI sudah adaptif. Artinya, seperti asesmen, UKBI disesuaikan
dengan kemampuan peserta uji. Yang lebih miris, tes UKBI bahkan belum dilakukan
di semua perguruan tinggi yang mempunyai prodi Bahasa Indonesia.
Tes
UKBI adalah salah satu cara kita untuk membuat bahasa Indonesia bermartabat
sebagai bahasa resmi. Lagi pula, secara yuridis, dalam Permendikbud Nomor 7
Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sudah disebutkan mengenai
kewajiban memakai UKBI untuk berbagai ragam profesi. Namun, implementasinya di lapangan
belum ada. Semestinya, implementasi UKBI pada perekrutan CPNS bisa menjadi cara
baru untuk mempromosikan dan memartabatkan bahasa Indonesia. Sayangnya,
kesempatan itu belum diambil. Pada masa mendatang UKBI harus menjadi tes wajib
untuk semua profesi.
Ada
Kemunduran
Jika
TOEFL dipersyaratkan di negara kita dan UKBI malah diabaikan, hal tersebut
merupakan sesuatu yang kurang logis. Harus dipahami bahwa bahasa Indonesia
sebagai bahasa nasional tidak hanya berfungsi sebagai bahasa percakapan dan
bahasa persatuan. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia juga sekaligus
mengandung fungsi dan gambaran kemampuan sintas, vokasional, akademis, hingga
profesional seseorang. Dalam hal ini, kepemilikan sertifikat UKBI yang sesuai
dengan peruntukannya harus menjadi kewajiban, terutama untuk bidang vokasi,
akademisi, dan profesi di negara kita.
Hal
itu masuk akal karena misi kita sesuai dengan amanat undang-undang, yakni
menginternasionalkan bahasa Indonesia. Internasionalisasi bahasa Indonesia tentu
saja harus dipandang sebagai sebuah kewajiban, bukan semata harapan. Artinya, langkah-langkah
teknis dan terukur dalam mewujudkannya harus dilakukan. Memang kita tak menampik
bahwa langkah-langkah teknis sudah mulai dilakukan. Prodi-prodi Bahasa
Indonesia di dunia internasional, misalnya, sudah digalakkan. Pengajar BIPA
(bahasa Indonesia bagi penutur asing) pun sudah dipersiapkan.
Beberapa
lomba untuk penutur asing pun sudah rutin dilakukan, seperti lomba baca puisi dan
lomba monolog. Namun, belakangan ini ada kemunduran terhadap agresivitas kita
dalam upaya penginternasionalan bahasa Indonesia. Di Australia, misalnya, animo
belajar bahasa Indonesia mulai menurun drastis. Tentu ada banyak penyebabnya.
Bisa saja hal tersebut terjadi karena kita cenderung lambat dalam kemajuan
ekonomi dan teknologi serta masih kurang bertaji dalam diplomasi budaya. Akan tetapi,
hal yang jauh lebih penting adalah sisi bahasa, terutama segi internal.
Betapa
tidak? Sudah bukan rahasia lagi bahwa kebanggaan kita berbahasa Indonesia
cenderung sangat lemah. Nomenklatur di negara ini, misalnya, masih dikuasai
bahasa asing. Pada kasus tertentu, nomenklatur dalam bahasa asing justru dibuat
menjadi gengsi dalam menaikkan pamor dan harga. Dengan begitu, akan selalu
lebih mahal fried chicken daripada ayam
goreng. Fried chicken akan tampil di
restoran mewah, sedangkan ayam goreng di kaki lima. Bermula dari situ,
muncullah penyakit warga Indonesia (pejabat hingga remaja) untuk selalu
menyisipkan bahasa asing pada kalimat-kalimatnya.
Pasalnya,
menyisipkan bahasa asing dianggap menjadi simbol kepintaran. Sesungguhnya, saya
tidak anti terhadap bahasa asing, apalagi takut (xenoglosofobia). Di dunia yang
mulai tak terbatas (bordeless) kita
memang harus tahu bahwa kita perlu menguasai bahasa asing. Hal ini sejalan dengan
pesan Badan Bahasa, yakni utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan
bahasa daerah. Namun, kita harus ingat bahwa kata kunci dari pesan tersebut
adalah kita harus tetap teguh dalam mengutamakan bahasa Indonesia, terutama
jika berdialog dengan orang Indonesia.
Sayangnya,
pengutamaan ini pelan-pelan menghilang dari kita. Di ruang publik di kota-kota
besar, misalnya, generasi muda Indonesia banyak yang fasih berbahasa asing,
tetapi malah gagap berbahasa Indonesia. Artinya, di negara kita saja bahasa Indonesia
mulai ditinggalkan dan ditanggalkan, apalagi di dunia internasional, seperti
Australia. Oleh karena itu, makin jelas bahwa hulu dari meredupnya bahasa
Indonesia adalah kita sendiri. Hal itu sudah diakui oleh George Quinn, dosen
pengajar bahasa Indonesia di Australian National University.
Mengapa
Kita Tidak?
Menurut
George Quinn, belakangan ini pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing makin
lesu justru karena orang di Indonesia sudah keranjingan berbahasa Inggris. Sudah
mulai ada rasa minder berbahasa Indonesia pada generasi muda. Menurut teori
David Crystal (2003), bahasa Indonesia akhirnya dipandang bukanlah sebagai simbol
kemajuan, melainkan simbol ketertinggalan. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat
undang-undang dan dasar negara, sebaiknya kita sudah harus memartabatkan bahasa
Indonesia dengan menjadikan kepemilikan UKBI sebagai syarat administratif untuk
berbagai jabatan di negara ini.
Dengan
menjadikan UKBI sebagai syarat administratif untuk berbagai profesi sebagaimana
diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2016, tentu sedikit banyak hal
tersebut akan menaikkan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan.
Kita tidak mau suatu saat bahasa Indonesia justru tergusur wibawanya atas nama
globalisme. Lagi pula, sebagai kekayaan negara sebagaimana tersaji dalam
konstitusi dasar, bahasa mempunyai kedudukan yang sama dengan bendera. Saya
tidak sedang berusaha untuk konservatif, apalagi primitif.
Namun, sebaiknya kita menyadari bahwa jika kita
selalu mengutamakan bahasa asing melalui berbagai aktivitas keseharian kita
(luring dan daring), hal itu tentu saja berarti kita sedang mengibarkan bendera
negara lain. Oleh karena itu, memartabatkan bahasa Indonesia dengan pendekatan
profesionalisme secara sesegera mungkin menjadi sangat mendesak rasanya bagi
kita. Bangsa lain bangga memartabatkan bahasanya dengan menjadikan serangkaian
tes, seperti UKBI, sebagai syarat administratif. Mengapa kita tidak? Semoga.
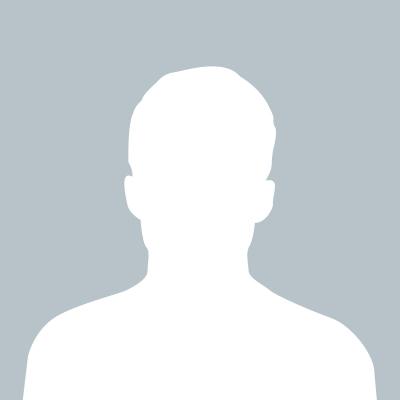
Riduan Situmorang
Guru Bahasa Indonesia SMAN 1 Doloksanggul Humbang Hasundutan , Instruktur Sastra Digital Tingkat Nasional, Aktif Berkesenian di Pusat Latihan Opera Batak (PLOt) Medan dan Toba Writers Forum (TWF).
