Absurditas dan Arkaisme Transformasi Sastra
Sesungguhnya
penggunaan kata dan kalimat adalah untuk menyampaikan maksud agar siapa
pun yang
membaca atau mendengarkannya dapat menangkap dan mengerti apa maksud kata
dan/atau kalimat yang disampaikan. Ada banyak kata yang ketika
diucapkan menimbulkan kesalahpahaman
penangkapan karena tidak didasari oleh pemahaman yang benar. Kesalahpahaman
itu muncul karena sumber literasi yang minim.
Dalam konteks
kalimat secara formal, terutama dalam pendidikan, penggunaan kata/frasa tidak terlepas dari unsur-unsur gramatikal (tata
bahasa) yang tersusun sesuai dengan
aturan baku. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan absurd dan arkais dalam konteks berbahasa? Pertanyaan itu muncul karena
adanya anggapan bahwa penggunaan kata/frasa terlahir dari kebebasan pemikiran individu yang
sering dihubungkan dengan kondisi sosial, terutama melalui
penggunaan media sosial yang begitu bebas.
Ada
kecenderungan di masyarakat, baik secara sadar maupun tidak, bahwa
penggunaan kalimat tidak lagi mengindahkan ejaan atau kaidah bahasa yang benar.
Itu tidak bersifat absolut (mutlak) bagi semua masyarakat. Namun, kecenderungan
itu terjadi karena pergeseran dan perubahan nilai-nilai sosial sebagai akibat dari
terjadinya revolusi pemikiran yang berada dalam kungkungan peradaban yang berbeda.
Perkembangan serta kemajuan dari ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi salah satu penyebab terbesar yang memengaruhi
ekosistem sosial. Oleh karena itu, adakalanya penempatan bahasa semata-mata
hanya sebagai alat komunikasi. Tekstur dan struktur menjadi tidak penting untuk
diperdebatkan.
Lantas bagaimana dengan semarak
perkembangan sastra tanah air? Ketika menelisik riwayat sastra, yang harus kita
akui belum masuk dalam strata industri, sastra seakan memunculkan dikotomi
baru. Jika pada masa silam ada pembatasan ruang dan waktu serta generasi
sastra, kini hal-hal seperti itu bukan lagi menjadi pagar pembatas. Artinya,
tidak ada lagi generasi yang berproses secara selektif dalam memosisikan
dirinya sebagai sastrawan. Siapa pun atau di mana pun banyak orang terobsesi
menjadi sastrawan. Hal itu terjadi karena tidak ada indikator yang jelas (nilai
objektivitas).
Pegiat sastra masih meyakini bahwa
proses seleksi alam untuk menjadikan label seorang sastrawan adalah dengan
pemuatan karya-karyanya melalui media, baik media konvensional (cetak) maupun
media digital. Selain itu, bagaimana konsistensi seorang pegiat sastra untuk
merefleksikan karyanya kepada pembaca?
Kini kita harus menyadari bahwa
dengan makin majunya teknologi digital, hal itu tentu memberikan perubahan
besar bagi para pegiat sastra. Dalam proses transformasi ini, banyak yang
menggunakan kecepatan teknologi untuk berkarya, kemudian secara instan karyanya
dapat dinikmati oleh para pembaca. Hal itu tentunya mendorong siapa pun untuk
terpacu atau terobsesi menjadi sastrawan sekalipun apa yang ditulisnya tidak
memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu, dalam konteks sastra harus ada
nilai yang mendasari mengapa orang harus menulis karya sastra.
Dengan mengutip catatan seorang
sastrawan yang sekaligus juga seorang akademisi—Budi Darma—saat ini banyak
orang terobsesi menjadi sastrawan. Orang hanya menulis tanpa mengerti maksud
dan tujuan menulis. Apa yang disampaikan dari pemikirannya semata-mata untuk
memuaskan dirinya. Lantas, apakah hasil menulis itu bisa dikatakan sebagai
sebuah karya sastra?
Lebih lanjut, dalam dimensi ruang
kreatif yang serbainstan dengan tersedianya media komunikasi, seperti gawai, hal
itu memudahkan siapa saja untuk menulis dan menyebarkan tulisannya. Sementara itu,
secara teorema analitik, karya sastra dapat dikatakan sebuah karya apabila
melalui proses seleksi serta pembuktian yang didasarkan pada asumsi secara
eksplisit, melalui kurator atau editor misalnya.
Jadi, secara logis ada batasan dalam
pengukuran kualitas dari sebuah karya sastra. Namun, dengan kondisi yang
dihadapi pada era globalisasi/digital seperti saat ini, orang cenderung memilih
cara instan untuk melepaskan ikatan teorema sastra. Dengan demikian, replika
karya sastra akan melahirkan bentuk-bentuk baru. Bentuk tersebut mengeliminasi
“kekuatan teori” serta menyublimasi persoalan sosial saat ini dengan
bentuk-bentuk absurd (tidak masuk
akal) dan arkais (tidak lazim dipakai
lagi/kuno).
Pertanyaannya adalah apakah
perubahan-perubahan itu dianggap sebagai sebuah pertentangan yang membatasi
kebebasan pemikiran? Dalam sebuah artikel oleh penulis sastra, Vito Prasetyo,
pernah digagas puisi yang terpenjara pemikiran. Itu terjadi karena puisi adalah
subjektivitas pemikiran yang melahirkan sebuah kebebasan berpendapat. Kemudian,
objek pembaca, terutama kalangan pecinta dan peminat sastra, sejatinya ingin
mendekatkan diri dengan bahasa-bahasa sastra yang lebih sederhana dan
mengedepankan bahasa metafora, hiperbol, personifikasi, simbolik, alegori, dan
lainnya.
Dalam perkembangannya, sastra mulai
mencari relevansi kebenaran yang melepaskan genre serta aliran-aliran sastra
yang kadang tidak lagi dianggap sejalan dengan dinamika sastra. Munculnya
egosentris karya sastra semata-mata karena tiap-tiap pegiat sastra ingin
mempresentasikan karyanya sebagai sesuatu yang berbeda. Sedikit banyaknya juga hal
itu karena terpengaruh oleh situasi dan kondisi sosial, yakni karya sastra
ingin sejajar dengan karya-karya seni lainnya.
Bagaimana dengan orientasi pengakuan
jika kemudian sebagian besar pegiat sastra mempresentasikan dirinya dan
terjebak dengan apa yang diistilahkan sebagai star syndrome (bermakna kondisi yang dialami seseorang sebagai
gambaran kepribadian seseorang yang merasa dirinya sempurna dan sangat
terkenal)? Dalam beberapa referensi literatur, kondisi semacam itu mengakibatkan
seorang pegiat sastra kerap melahirkan karya-karya sastra yang memiliki analogi
dengan karya absurd dan arkais.
Lebih lanjut, perekaan karya-karya
absurd sebetulnya sudah berlangsung beberapa puluh tahun. Dalam konsep disiplin
ilmu, aliran absurdisme sebetulnya diadopsi dari ilmu filsafat, yakni pembaruan
sebuah paham aliran eksistensialisme. Tokoh pencetus aliran absurditas sastra
adalah Albert Camus, seorang filsuf yang juga seorang jurnalis berkebangsaan
Prancis. Konsep absurdisme dipopulerkan oleh Albert Camus dengan buku berjudul Mite Sisifus. Buku itu berisi tentang
bagaimana sebuah realitas bertentangan dengan nalar.
Bagaimana halnya dengan karya yang
bernuansa arkais? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata arkais
memiliki pengertian ‘berhubungan dengan masa dahulu atau berciri kuno, tua’ dan
juga ‘tidak lazim dipakai lagi (tentang kata)’. Sementara itu, dalam karya
seni, itu dapat memberikan arti tersendiri (nilai). Bagi pengamat seni, sastra
juga sebagai dimensi seni yang melahirkan nilai seni dalam penggunaan aksara.
Dalam telaah zaman, realitas karya
sastra yang menggabungkan konsep absurd dan arkais menimbulkan konflik atau
pertentangan bagi pembaca. Namun, pada sisi tertentu karya sastra yang dihasilkan
dari aliran ini begitu mengasyikkan. Tentu itu merupakan penangkapan pembaca
dari nilai seni. Itu karena seni adalah realitas yang tidak harus ditampilkan
dalam wujud nyata (realis).
Dalam catatan perjalanan karya
sastra, ada beberapa nama sastrawan yang dimunculkan sesuai dengan masanya. Dalam
aliran absurdisme, ada beberapa pengarang fiksi/sastra yang dikenal, seperti
Franz Kafka, Albert Camus, Nobokov, Samuel Beckett, Flan Brien, Eugene Ionesco,
dan Arthur Adamov. Sementara itu, di Indonesia ada Iwan Simatupang, Putu
Wijaya, dan Arifin C. Noer. Namun, jika kita menelisik lebih jauh dalam
beberapa karya sastra, seperti puisi contohnya, ada beberapa puisi yang juga
bisa dikategorikan bernuansa atau memiliki kesamaan genre dengan konsep
absurdisme.
Sebelum kemerdekaan Republik
Indonesia, ada beberapa puisi yang dihasilkan oleh penyair yang sangat kental
dengan warna atau nuansa absurditas. Salah satu contohnya adalah puisi karya Chairil
Anwar yang bertajuk “Derai-Derai
Cemara” dan “Malam”. Di dalamnya terdapat sebuah kalimat
atau sebuah kata yang seolah-olah hanya seorang Chairil Anwar yang mengerti
maknanya. Oleh karena itu, pembaca mereka-reka subjektivitas pemikirannya.
Dalam puisi berjudul “Derai-Derai Cemara” terkandung makna ‘kematian’ dalam
pikiran Chairil Anwar sehingga tidak terjangkau dengan nalar logis pembaca. Demikian
halnya dengan peletakan kata thermopylae dalam
sajak “Malam”. Itu yang kemudian membuat pembaca
mereka-reka dengan keterbatasannya yang mungkin akan menjadi pertentangan
konflik pikiran dengan perspektif (sudut
pandang) yang berbeda. Bisa jadi, sebelum tercetusnya aliran absurdisme, ada
banyak karya fiksi yang dibuat oleh pengarang tanpa dalil pembenaran sebuah
aliran.
Pertanyaannya adalah apakah beberapa
sastrawan Indonesia saat ini juga melakukan eksperimen karya di jalur
absurdisme? Tentu hal itu tidak bisa dimungkiri karena dengan kemajuan
teknologi digital, sastrawan pun ikut berpacu menghasilkan karya-karyanya dan
sangat bergantung pada media sosial (medsos). Jadi, medsos mempunyai peran yang
sangat vital, terutama sebagai wadah media pembelajaran. Itu mungkin yang berimbas
pada pergeseran karya-karya sastra karena kejenuhan dengan sastra lama
bernuansa klasik atau karena pertentangan ketidakpuasan terhadap aliran-aliran
sebelumnya.
Dalam pandangan bijak dengan
merefleksikan kondisi saat ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa semarak
kehidupan sastra sangat dinamis. Namun, sayangnya hal itu tidak terbangun
dengan konsep desain dan pola yang jelas. Seorang pengarang fiksi, baik cerpen,
puisi, maupun karya lainnya hanya terbangun dari konsep mengasah bakat sebagai
penulis. Bahkan, kadang penulis tidak memiliki tujuan yang jelas, mengapa ia
harus menulis puisi atau cerpen. Mereka sekadar menuangkan ide dan gagasan.
Seyogianya konsep tekstual dan kontekstual harus berbanding lurus.
Sebuah transformasi sastra menjadi terpolarisasi
karena tidak terbangun dari konsep tujuan yang jelas. Memang, dalam etika dan
estetika sastra tidak ada batasan yang menyekat ruang dan dimensi. Siapa pun
boleh menulis karya fiksi. Makin banyaknya pengarang fiksi yang berkarya,
tentunya secara alamiah juga akan memunculkan seleksi alam untuk menghasilkan
karya-karya bagus meski dengan segala lika-liku sebuah subjektivitas, baik pemikiran
maupun faktor lainnya.
Sebagai penyelarasan akibat
terjadinya transformasi era, tentu juga dibutuhkan kematangan wawasan dalam
menyampaikan bahasa-bahasa sastra. Tidak hanya penguasaan sumber-sumber
literasi, tetapi juga diharapkan ada riset mendalam bagi pegiat sastra. Kita tidak
boleh terjebak dengan sastra identitas. Apalagi jika itu melahirkan embrio baru
yang hanya untuk memuaskan segelintir orang sebagai pengakuan identitas, baik
secara perseorangan maupun kelompok/komunitas. Itu akan menjadi endemi sastra pada
era yang akan datang.
Dalam tinjauan penulis, untuk
menghasilkan karya-karya sastra yang monumental, pengarang fiksi semata-mata
tidak hanya berorientasi sesaat. Minimal karya sastra itu menjadi wahana
pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih dekat dengan hal-hal yang positif. Contohnya
adalah sebagai alat untuk mempertahankan nilai-nilai ekosistem budaya. Selain
itu, karya sastra bisa menjadi alat untuk meningkatkan kemahiran berbahasa bagi
masyarakat. Itu bukan sekadar sebuah typo
karena terjebak dengan transformasi sastra yang berorientasi pada absurditas
dan arkaisme karya. ***
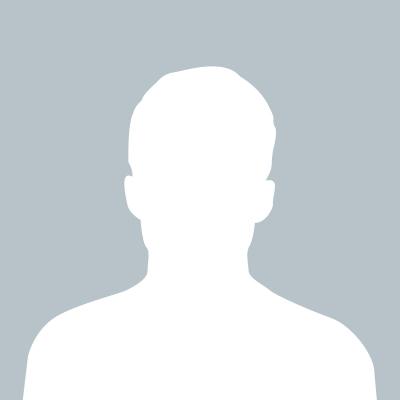
Vito Prasetyo
Penulis adalah sastrawan serta peminat bahasa dan budaya.
