Sastra Kepejalanan: Mengulas Novel-Novel Jazuli Imam
Sastra adalah sebuah ilmu lama yang perkembangannya masih terus
berjalan sampai hari ini. Keberagaman dan perkembangannya tidak berhenti karena
sifat sastra sendiri dapat dikatakan “luwes”
hingga dapat dipadupadankan dengan berbagai ilmu lain serta pandangan atau
paradigma yang beraneka ragam. Jenis dimensi dan penggabungan ilmu dengan sastra
memunculkan pandangan-pandangan baru tentang sastra itu sendiri.
Salah satu contohnya adalah sastra keagamaan. Sastra dan agama
dapat dipadukan dengan berbagai ragam penafsiran karena
dalam definisi yang singkat, sastra berarti sesuatu
kegiatan kreatif, sebuah karya seni (Wellek & Warren, 2016). Dari definisi singkat tersebut, dapat
dikatakan secara eksplisit bahwa sastra dapat berupa penggambaran apa
saja dan dapat menimbulkan pandangan yang beraneka rupa.
Seperti grup musik yang memiliki berbagai macam genre, mulai dari
dangdut hingga punk rock, sastra pun
tidak kalah dalam berbagai jenis genre dan kekhasannya. Misalnya, karya sastra karangan K.H. Mustofa Bisri (Gus Mus) konsisten dengan
unsur religiositasnya, tulisan-tulisan Djenar Maesa Ayu mengekspresikan
perempuan dan pengarang, serta gaya khas tersendiri yang dimiliki sastrawan lain menjadikan gaya
tersebut melekat pada dirinya. Kemudian, muncul pertanyaan, apakah
genre atau gaya bersifat tetap? Wellek dan
Warren dalam buku Teori Kesusastraan (2016: 276)
mengatakan, “Mungkin tidak.” Dengan sifat “luwes”
sastra seperti disinggung di awal, dengan adanya pandangan dan karya-karya baru
yang terlahir, bisa saja kategori tentang sastra bergeser.
Pandangan kita terhadap sastra yang mengandung unsur-unsur tertentu
merupakan genre atau nilai sastra yang terkandung dalam setiap karya yang lahir
melewati pengindraan mendalam oleh pengarangnya, seperti
sastra dan masyarakat yang kental pada karya-karya Ahmad Tohari, ekspresi
perempuan pada Saman karya Ayu Utami, serta kearifan lokal dan kebudayaan yang
tergambar pada Celurit Hujan Panas karya Zainul Muttaqin. Beragam
penggambaran tentang ekologi, sosial, religiositas, serta kebudayaan terdapat pada ketiga novel Jazuli Imam (Pejalan
Anarki, Jalan Pulang, dan Sumi).
Sebelum membicarakan ketiga novel tersebut, kita akan selami gaya bersastra Jazuli Imam
terlebih dahulu. Juju (sapaan
akrab Jazuli Imam) merupakan seorang penulis dan pengembara yang fokus
menyuarakan keberpihakannya pada alam, masyarakat tertindas, dan dunia konservasi.
Dari situlah muncul istilah pejalan yang dipopulerkan pada ketiga novelnya. Menurut KBBI,
kata pejalan berarti orang yang suka atau biasa berjalan. Dalam artian yang general semacam itu, kita bisa memaknai
siapa saja yang dapat berjalan atau yang biasa berjalan kaki merupakan “pejalan”. Namun, tidak hanya sebatas
demikian kita dapat memaknai kata pejalan.
Kata pejalan memang
sekilas terdengar seperti traveller atau avonturir. Namun, lebih
dalam lagi, pejalan dapat dimaknai sebagai manusia yang melakukan sebuah
perjalanan di mana pun dan kapan pun. Dalam
perjalanannya itu, manusia tersebut dapat belajar
betul terhadap kondisi tempat barunya mulai dari
kehidupan masyarakatnya, budayanya, spiritualnya, bahkan sampai hal-hal yang
menyangkut adat dan norma yang berlaku pada tempat tersebut. Ketika
kembali ke tempat asalnya, manusia yang dikatakan sebagai “pejalan” itu
dapat menjadi manusia yang lebih baik daripada
sebelumnya karena telah belajar dari perjalanannya.
Kaitannya dengan karya sastra, kepejalanan menjadi sebuah gaya baru
bercerita yang coba dikampanyekan oleh pengarang yang memiliki latar belakang
sebagai pencinta alam. Febrialdi R. (@edelweisbasah) sukses dengan melahirkan novel
berjudul Bara dan Gitanjali serta pengarang bernama Prasetyo Aditya
(@pengedarkata) melahirkan novel berjudul Berdamai dengan Letusan.
Istilah sastra kepejalanan merujuk pada
dua kata, yaitu sastra dan pejalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sastra
kepejalanan adalah bentuk atau gaya bersastra yang di dalamnya termuat
banyak pandangan atau paradigma tentang sebuah cerita perjalanan yang berisikan
banyak pelajaran tentang kecintaan terhadap alam, ekspresi manusia dan
masyarakat, religiositas dan spiritualitas, budaya, serta ajaran moral yang
terkandung di dalamnya.
Contoh sastra kepejalanan ini dapat ditemukan dalam novel-novel
yang dikarang oleh Jazuli Imam. Pada novel yang berjudul Pejalan Anarki, Jazuli
Imam menceritakan kisah hidup tokoh bernama El yang bertahan hidup sendiri
untuk mencukupi kebutuhannya. El berkuliah di kampus swasta
di Yogyakarta dengan biaya hidup sendiri yang didapat dari usahanya mengelola brand pakaian outdoor. Kemandirian, relasi, dan sikap berjuang El untuk dirinya
menjadi sorotan dalam novel ini. Pejalan Anarki juga menggambarkan
paradigma baru tentang kehidupan. Di novel ini disajikan suatu penerapan
idealisme yang dilakukan oleh tokoh El dalam konsistensinya menjaga dan
melakukannya.
"Segala bentuk ketergantungan adalah penjajahan."
(hlm. 309)
“Aku wajib malu pada kehidupan, jika merasa bersedih dan bisa
menangis saat diri disakiti, namun baik-baik saja melihat segala kekeliruan
yang menyedihkan di dunia." (hlm. 33)
Kepejalanan dalam Pejalan Anarki juga
tergambar dari El yang seorang pejalan. Dalam kisahnya, El kenal dengan
berbagai macam golongan masyarakat. Anak-anak kecil, orang-orang di desa, serta
namanya yang cukup tenar di dunia pencinta alam diceritakan di dalam novel. Religiositas juga terdapat
pada novel ini, seperti pencarian makna tentang Tuhan yang digambarkan dalam
sebuah kutipan berikut.
"Jika kau butuh lebih dari sekedar tafsiran tentang siapa itu
Tuhan, teman, dan diri sendiri, pergilah mendaki gunung atau mengheninglah."
(hlm. 16)
Masalah atau persoalan sosial juga
dibahas dalam novel ini. Penghargaan
terhadap manusia juga diungkap Jazuli Imam dalam paradigmanya memandang
manusia.
"Sekolah, titel, gelar, dan semacamnya itu, sekarang cuma jadi topeng dari kebodohan banyak manusia. Seorang dengan kecerdasan, ia tidak butuh gelar untuk diakui. Perbuatannya, karyanya, manfaat-manfaat yang diciptakan bagi sekitar adalah sesuatu yang membuat ia dianggap hidup." (hlm. 275)
Begitu
juga dalam pandangannya terhadap kekerasan yang disampaikan melalui kutipan berikut.
"Kekerasan adalah manifestasi kebodohan terbesar manusia."
(hlm. 295)
Dalam novel ini, Jazuli Imam juga memperkenalkan kata anarki yang sudah
mendapat citra buruk dari kebanyakan masyarakat
Indonesia. Kata anarki yang dalam KBBI berarti kekacauan dipatahkan oleh sosok El yang berpenampilan
urakan, tetapi memiliki kelembutan dan jiwa sosial
tinggi. Novel Pejalan Anarki ini menjadi pembuka bagi pembaca untuk lebih memahami arti
kepejalanan dalam karangan Jazuli Imam yang lain, yaitu Jalan Pulang yang
menceritakan tokoh sentral Sekar, tokoh yang diceritakan
sama seperti tokoh El di novel sebelumnya. Novel Pejalan Anarki dan Jalan
Pulang merupakan dwilogi yang diberi judul Sepasang yang Melawan.
Novel kedua yang berjudul Jalan Pulang ini
menceritakan lanjutan kisah El dan Sekar yang kini sudah memiliki frekuensi
pemikiran yang sama, pemikiran “pejalan”.
Berbeda dengan novel pertamanya yang berbicara tentang idealisme dan sosok “anarki” El,
Jalan Pulang bisa dianggap lebih “romantis”
karena banyak berisikan puisi yang ditulis oleh El kepada Sekar. Selain
berfokus pada Sekar, di buku ini kita juga akan diperkenalkan dengan sosok
perempuan hebat lain bernama Eliza Puteri, seorang
guru muda yang mengajar di sebuah distrik kecil di Merauke, Papua. Bersama
dengan Eliza, kita diajak untuk mengikuti liku-liku
birokrasi dan wajah pendidikan di timur Indonesia.
Kritik sosial yang dilakukan Jazuli Imam pada novel keduanya ini
menyoroti sistem pendidikan di Papua yang jauh dari kata layak seperti di
daerah-daerah Indonesia yang lain. Jalan Pulang juga banyak memprotes
kebijakan-kebijakan lain di Papua yang dianggap keliru dan merugikan, terutama
mengenai penebangan hutan, deforestasi, penambangan, degradasi lahan,
pencemaran lingkungan, hingga konflik-konflik yang biasa terjadi di batas
negara.
Dwilogi ini (Pejalan Anarki dan Jalan Pulang) memberi
gambaran tentang sastra dan dunia kepejalanan yang erat untuk disuarakan, mulai
dari religiositas, sosial masyarakat, bahkan sampai masuk ke ranah pendidikan,
politik, dan ketertindasan yang terjadi di ujung
timur wilayah Indonesia.
Novel ketiga yang juga menjadikan Jazuli Imam layak diselami
sebagai pengarang berhaluan “pejalan” adalah novel berjudul Sumi. Novel ini menceritakan perjalanan
seorang tokoh bernama Sumi di daerah bernama Ujung Timur. Ujung Timur yang
diceritakan dalam novel ini dapat kita terka sebagai Papua karena narasi-narasi
dalam novel ini menggambarkan suku-suku tradisional, keindahan alam berupa
hutan dan kekayaan satwa, serta kondisi geografis yang pembaca dapat dengan
mudah menebak lokasi bahwa latar dalam novel tersebut adalah Papua.
Peristiwa seperti eksploitasi hutan berupa alih fungsi menjadi
lahan sawit dan deforestasi yang dilakukan di Ujung Timur ini menjadi fokus
utama cerita yang terjadi pada tokoh Sumi. Selain
itu,
diceritakan pula kisah keluarganya yang menjadi penyebab
Sumi pergi dari rumah dan meninggalkan pekerjaannya di kantor asuransi.
Sumi menyimpan unsur-unsur yang kompleks,
seperti konflik batin yang dialami karena tekanan keluarga hingga peristiwa
rasisme yang terjadi di Indonesia (mengutip kejadian rasisme
terhadap Papua di Jawa).
“Sumi tidak menangis, sebab Ayah tidak menyukai orang yang cengeng.
Ayah akan marah jika Sumi menangis, meski Ayah tahu Sumi tidak menyukai orang
yang marah.” (hlm. 1)
“Televisi dan radio ramai memberitakan
berita buruk tersebut. Stigma perusuh dan subversif bagi pemuda Ujung Timur
bersilarat di media. Satu hari setelahnya, kabar serupa ramai tersiar; sebuah
asrama mahasiswa Ujung Timur di Yogyakarta digeruduk ormas yang sama. Entah apa
relasinya, yang pasti, di Jakarta dan di Yogya, seragam khas ormas terbesar
kedua di negara itu adalah barisan paling dominan yang melakukan sweeping ke asrama, rumah kontrakan,
kos-kosan, dan semua tempat yang disinyalir menjadi tempat tinggal orang-orang
timur.” (hlm.
190)
Selain konflik batin dan rasisme yang
diceritakan dalam novel Sumi, Jazuli
Imam juga menjelaskan dengan narasi yang apik tentang kerusakan hutan yang
terjadi di Ujung Timur dan juga nilai religius agama Buddha yang disampaikan oleh tokoh Meta,
seorang tokoh yang ditemui Sumi ketika Meta sedang melakukan touring dengan rombongan vespanya.
"Deforestasi besar-besaran sedang
dilakukan dan akan terus terjadi di hutan Ujung Timur, yang terbesar adalah
yang berada di hutan Jantung Timur. Perusahaan kayu dan perkebunan sawit adalah
dua hal utama di balik itu semua selain pembukaan sawah padi.” (hlm. 161)
“Dedaunan liar tidak mengganggu, duri
tidak menyakitkan, pohon tumbang tidak menyulitkan, bebatuan cadas tidak melukai,
babi hutan tidak mencuri, kemudian udara dingin atau badai tidaklah membunuh.
Pandangan yang seperti itu bermula dari cinta kasih.” (hlm. 145—146)
Pejalan Anarki, Jalan Pulang, dan Sumi menjadi sebuah pandangan
atau daya tangkap terhadap realitas yang dilakukan oleh Jazuli Imam. Melalui
karyanya, pandangan baru berupa karya sastra yang mengandung makna “pejalan” dapat ditangkap oleh pembaca yang
melakukan pembacaan kritis atas karya sastra yang dilahirkan Jazuli Imam.
Kepejalanan ini digambarkan pada cerita-cerita di setiap novel yang ditulisnya.
Sastra kepejalanan yang terkandung ini menjadi sebuah paradigma baru dalam
genre dan gaya khas dalam kepenulisan sastra modern di Indonesia. Sastra
kepejalanan menjadi sebuah pandangan baru dalam sebuah kacamata dalam memandang
karya sastra. Pada perkembangannya, dimensi sastra yang lain pun akan terus
lahir dan berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan manusia dan daya
cipta pengarang dalam menghasilkan karya sastra pada masa mendatang.
Daftar Bacaan
Imam, Jazuli. (2016). Pejalan Anarki. Yogyakarta:
Djelajah Pustaka.
Imam, Jazuli. (2016). Jalan Pulang. Yogyakarta:
Djelajah Pustaka.
Imam, Jazuli. (2020). Sumi. Yogyakarta:
Djelajah Pustaka.
Wellek, R., & Warren, A. (2016). Teori Kesusastraan. Jakarta: PT. Gramedia.
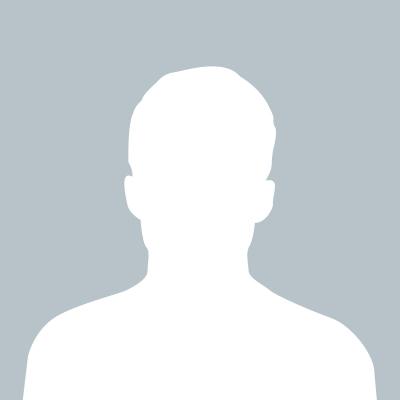
Bayu Suta Wardianto
Bayu Suta Wardianto lahir di Tegal pada 18 Maret 1998. Penulis merupakan mahasiswa pascasarjana Universitas Muhamadiyah Purwokerto, tim pengelola Lembaga Kajian Nusantara Raya, dan peneliti di Pusat Riset Wadas Kelir Purwokerto.
