Mengenang Abdul Hadi W.M.: DNA Sastra Bangsa Indonesia Tertelusur dari Barus
Sastrawan/ilmuwan
Abdul Hadi W.M. (Wiji Muthari) kini telah tiada. Berita duka atas meninggalnya Peneroka
DNA Sastra Bangsa Indonesia ini beredar pada Jumat pagi, 19 Januari 2024. Duka
cita sangat mendalam dengan teriring doa semoga karya/ilmu beliau ditakar
menjadi amal salehnya.
Semasa
hidup (di dunia akademis), Abdul Hadi berhasil menelusuri jejak sastra pembawa
bibit-bibit bahasa Indonesia. Bahasa persatuan bangsa ini ditemukan berjejak di
Barus. Ini merupakan sebuah kenangan—sekaligus harapan—yang amat mulia dari keseriusan
hasil kajian Abdul Hadi dalam kebersamaannya dengan ilmuwan/sastrawan yang lain.
Temuan Kosakata Serapan: Asing dan Daerah
Temuan
Abdul Hadi di bidang ilmu kebahasaan/kesastraan sangatlah bermakna untuk
mengungkap informasi dasar sifat hidup berkeindonesiaan atau apa yang—oleh Kementerian
PPN/Bappenas melalui paparan Didik Darmanto pada 22 November 2023—disebut sebagai
DNA sastra bangsa Indonesia. Pada
kesempatan diskusi perencanaan pembangunan nasional itu, paparan Direktur Agama,
Pendidikan, dan Kebudayaan tersebut menggambarkan arah pembangunan bahasa dalam
kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025—2029.
Sebelumnya,
pada 21 Mei 2023, arah kebijakan pembangunan bahasa—secara khusus
untuk program pengembangan dan pembinaan bahasa pada 2024—juga telah dipaparkan
oleh Amich Alhumami (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan
Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas). Dalam paparan itu, substansi keluhuran
bahasa Indonesia beserta unsur sastra dan budayanya dimuat sangat lengkap dari urutan
pertama dengan menunjukkan keunggulan tokoh Hamzah Fansuri—sastrawan/budayawan
Melayu Barus (peradaban abad ke-16 M)—yang dijadikan objek penerokaan akademis
oleh Abdul Hadi.
Memang
tidak sendirian, Abdul Hadi meneroka DNA sastra bangsa Indonesia yang bergerak di
Negeri Melayu Barus. Pada 18—21 Desember 2002, beliau bergabung dengan Balai
Bahasa Medan (sekarang Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara) sebagai pemakalah kunci
dalam kegiatan Seminar Internasional
Tapak Sufi Hamzah Al-Fansuri yang diadakan di Kota Sibolga: tak jauh dari episentrum peradaban Nusantara di Barus. Dalam
pandangan anggota panitia kegiatan (Wawan Prihartono, 24 Januari 2024 dalam
komunikasi pribadi), seminar itu dilakukan karena tonggak kepeloporan sastra
Indonesia jarang disebut oleh tokoh sastra di dalam negeri sendiri.
Sementara
itu, Hamzah Fansuri justru lebih populer di luar Indonesia. Kemasyhuran sastrawan
Barus ini dipelajari sangat serius oleh Abdul Hadi, antara lain, dengan merujuk
kajian terdahulu De Geschriften van
Hamzah Pansoeri dari Johann Doorenbos (terbit di Leiden, 1933). Karya tulis
M. Naquib Al-Attas (disertasi di Universitas Oxford, Inggris, 1968) dengan
tajuk The Mysticism of Hamzah Fansuri
(terbit di Kuala Lumpur, 1970) juga merupakan sumber rujukan utama, selain
rujukan dari karya G.W.J. Drewes dan I.F. Brakel (1986) dengan judul Poems of Hamzah Fansuri (Hadi, 2020: 5).
Masih
banyak akademisi lain yang turut serta menelusuri pergerakan DNA sastra bangsa
Indonesia di Negeri Melayu Barus. Sejumlah pakar dari tiga negara—Indonesia,
Malaysia, dan Thailand—hadir menyajikan makalahnya masing-masing dalam seminar tersebut.
Termasuk dalam daftar pemakalah seminar internasional pada 2002 itu ialah Abdul
Razak Zaidan: seorang sarjana sastra dari Pusat Bahasa atau—sekarang—Badan Bahasa,
Kemendikbudristek, RI. Sebagaimana tertulis
dalam pengantar buku laporan seminar yang disusun oleh Shafwan Hadi Umry dkk. (2003),
Hamzah Fansuri disebut sebagai “peletak dasar sastra modern Indonesia”.
Lalu,
apa hubungan pendasarannya dengan perkembangan bahasa (dan sastra) Indonesia
terkini? Ternyata, sejak awal—ketika masih mengalami pembibitan (terhitung hingga abad
ke-16 M)—bahasa Indonesia diketahui sifat dasarnya dalam hal menyerap kosakata bahasa
asing. Pengetahuan empiris inilah yang tampak amat berharga disumbangkan oleh
Abdul Hadi (2002) dari kajian hermeneutiknya atas syair Hamzah Fansuri. Dari
penyair Barus ini—dalam perspektif kebahasaan—ditemukan tidak kurang 1.200 kata Arab dan Persia.
Kata yang mengalir indah sebagai gerakan sukma Hamzah Fansuri diserap sebagiannya
dari kandungan ayat dan peristilahan dalam Al-Qur’an (baca Hadi, 2020: 445—447).
Dari
pengalaman empiris Abdul Hadi, diketahui pula hakikat bahwa bahasa
Indonesia—sekali lagi, masih pada tahap pembibitan (jauh sebelum bahasa
persatuan ini berhasil dibentuk pada abad ke-20)—juga bersifat menyerap
kosakata bahasa daerah. Dalam buku terbitan PT Kompas Media Nusantara pada 2020 tersebut, secara khusus (baca halaman 466—468), Abdul Hadi membuat senarai kosakata
serapan daerah yang dimanfaatkan oleh Hamzah Fansuri, yaitu serapan dari bahasa
Melayu dan Jawa (seperti kata payu ‘laku;
laris’). Pemanfaatan kosakata serapan, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing,
ditemukan dalam syair Syekh Barus seperti ini.
Hamzah Fansuri
di Negeri Melayu
Tempatnya
kapur di dalam kayu
Asalnya
manikam dimanakan layu
Dengan
ilmu dunia dimanakan payu
(Ikat-ikatan
XV dalam Abdul Hadi, 2003; 2020: 409)
Hamzah
miskin orang ‘uryani
Seperti
Ismail jadi qurbani
Bukannya
‘Ajami lagi ‘Arabi
Nentiasa
wasil dengan Yang Baqi
(Ikat-ikatan
XIX dalam Abdul Hadi, 2003; 2020: 417)
Penyair
Barus tersebut diketahui memang sangat piawai memanfaatkan kosakata serapan
sebagai tamsil atau citraan simbolik dari alam dunia di sekitar kehidupan dan
kisah dari Al-Qur’an (dalam hal contoh di atas kisah Nabi Ismail a.s.).
Keindahan kata dalam syair sufistik berpola AAAA itu menggambarkan luasnya pengembaraan
dan pengalaman transendental sang sufi. Dalam hal ini, Abdul Hadi (2003; 2020) menegaskan
bahwa Hamzah Fansuri sangat akrab dengan lingkungan kota kelahirannya di Barus dalam
kekhasan sosial masyarakatnya.
Pada
masa gerakan sastra sufi Hamzah Fansuri—sebut saja di sini sebagai gelombang
awal dalam pergerakan DNA sastra bangsa Indonesia—Barus masih merupakan
pelabuhan yang ramai dikunjungi kapal asing. Di kawasan Kota Barus, telah berlangsung
perdagangan kamper atau kapur barus selama berabad-abad; ribuan tahun silam, seturut
dengan kajian antropologi bahkan sejak era Nabi Musa a.s. (Tumanggor, 2017; 2019).
Begitu pentingnya barang perniagaan tersebut sehingga kosakata khas dari
Indonesia ini, yakni kafura ditemukan
terserap ke dalam Al-Qur’an (baca Surah Al-Insan: 5).
Gelombang Sastra Sufi setelah Hamzah Fansuri
Terbentuklah
gelombang baru setelah gerakan sastra sufi Hamzah Fansuri di Barus. Gelombang
baru dimaksud mulai terbentuk pada permulaan abad ke-17 ketika peranan Barus
sebagai pelabuhan dagang internasional mulai merosot. Abdul Hadi mencatat kemerosotan
Barus tersebut berkelindan dengan munculnya Kerajaan Aceh Darussalam melalui
pembangunan pelabuhan di pantai barat Sumatra yang berhadapan dengan Selat
Malaka.
Berdasarkan
kajian Abdul Hadi, sastra sufi Hamzah Fansuri diketahui tetap bergerak hidup
secara berkelanjutan sekurang-kurangnya tiga abad. Episentrum pergerakan DNA
sastra bangsa Indonesia memang terbukti berubah dari semula pada titik pusat
perdagangan kapur barus di pantai barat Sumatra yang berhadapan langsung dengan
Samudra Hindia (Samudra Indonesia). Kemudian,
pergerakan sastra ini berlangsung di seputar Negeri Melayu (Selat) Malaka. Di
kawasan pantai timur Sumatra inilah mulai terbentuk bahasa Indonesia.
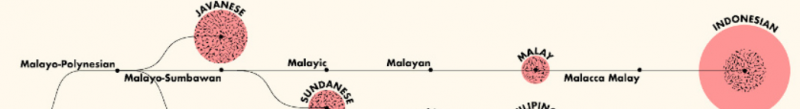
(diekstrak
pada 25/01/2024 (sekitar pukul 04.30 WIB) dari sumber https://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/)
Gambar/peta kebahasaan di atas
merupakan ilustrasi sumber awal pada bahasa Indonesia (Indonesian) yang beberapa abad kemudian dituturkan sebagai bahasa
kesepuluh dari seratus bahasa berpenutur terbanyak sedunia (laporan Iman Ghosh,
15 Februari 2020). Sumber awal terbentuknya bahasa Indonesia tersebut
digambarkan sangat jelas pada titik kebahasaan Melayu (Selat) Malaka dengan
garis lurus dari sumber kebahasaan yang jauh lebih awal, yaitu Melayu-Polinesia
(Austronesia). Sayangnya, ilustrasi itu tidak/belum menunjukkan titik peradaban
Nusantara di Negeri Melayu Barus.
Pada
masa peradaban Melayu di seputar kawasan (Selat) Malaka tersebut, terdapat seorang
tokoh terkemuka dalam sastra sufi, yakni Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Oleh
Kementerian PPN/Bappenas (2023), tokoh Raja Ali Haji—yang juga bereputasi dunia
internasional, antara lain, dengan mahakarya Gurindam Duabelas—dicantumkan pada urutan kedua setelah tokoh
pertama: Hamzah Fansuri. Seturut dengan arahan Kementerian PPN/Bappenas itu, gelombang
sastra sufi di kawasan pantai timur Sumatra perlu dibaca sebagai pergerakan
yang berkesinambungan dengan Melayu Barus melalui peradaban Nusantara yang
dibangun di Aceh, secara khusus melalui Syams Al-Din Pasai sebagai murid Syekh
Hamzah Fansuri (Hadi, 2020: 121).
Secara
lebih khusus, dapat disebut sangatlah penting peranan Kerajaan Aceh Darussalam
untuk memulai pembentukan bahasa persatuan ini. Dalam sejarah terbentuknya
bahasa Indonesia, kamus tertua (terbit pada 1603 di Amsterdam) disusun oleh
Frederick de Houtman selama hidup 26 bulan dalam penjara di Benteng Pidi, Aceh.
Penyusunan kamus itu merupakan perikutan dari peristiwa heroik Laksamana
Malahayati yang menewaskan Cornelis de Houtman dalam duel satu lawan satu di
atas geladak kapal pada 11 September 1599 (https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/4117/keluhuran-bahasa-indonesia-dan-legasi-malahayati-di-unesco).
Hasil kajian Abdul Hadi telah menggambarkan bahwa pergerakan DNA sastra bangsa Indonesia terjadi secara bergelombang dengan membawa perikehidupan sosial-masyarakat bahasanya. Sesuai dengan teori pergerakan sosial (“social movement” dalam istilah Jamison dan Eyerman, 1980; 1991), gelombang pergerakan dimaksud dapat dibaca dalam tiga siklus sebagai tahapan pembibitan, pembentukan, dan konsolidasi pergerakan bahasa dan sastra Indonesia. Pergerakan berkeindonesiaan itu—sekarang, pada abad ke-21 M—diketahui berada pada siklus konsolidasi. Dalam hal itu, kajian Abdul Hadi dapat memberikan konfirmasi adanya siklus perikehidupan berkeindonesiaan—dari aspek kebahasaan/kesastraan—lebih dari tiga abad setelah gerakan sastra sufi Hamzah Fansuri di Barus.
Gema Sastra Sufi dari Sanusi hingga Sutardji
Karya tulis Abdul Hadi (2022) yang bertajuk “Gema Sufi dalam Sastra Indonesia: Dari Sanusi Pane Sampai Sutardji” merupakan makalah kenangan dalam kebersamaannya dengan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Kemendikbudristek, yang pada 20 Februari 2022 menggelar seminar nasional untuk mengusung kepahlawanan tokoh Sanusi Pane. Mafhum bahwa Sanusi bertindak sebagai tokoh penggerak atas gagasan bahasa persatuan Indonesia yang sempat macet dalam perdebatan sengit antara M. Yamin dan M. Tabrani pada 2 Mei 1926 ketika hasil Kongres Pemuda Indonesia (Pertama) dirumuskan.
Setelah terjadi peristiwa akbar Sumpah Pemuda 1928, terbentuklah angkatan sastra Pujangga Baru (1930-an) yang tentu saja merupakan bagian penting dari pergerakan DNA sastra bangsa Indonesia. Pada seminar yang digelar dalam musim pandemi Covid-19 tersebut, Abdul Hadi berbicara secara spesifik tentang Sanusi Pane sebagai tokoh teras Pujangga Baru dengan semangatnya dalam bersastra sufistik. Karya sastra Sanusi dengan kecenderungan untuk mengungkap pengalaman kerohanian guna mencari kebenaran di jalan tasawuf atau cinta Ilahi merupakan keberlanjutan tradisi sastra Indonesia dari penyair sufi Hamzah Fansuri pada abad ke-16 M.
Pada kesempatan bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara itu, Abdul Hadi secara tegas menyatakan bahwa gema sastra sufi Hamzah Fansuri masih sangat terasa gaungnya dalam sajak Sanusi Pane yang terkenal dengan judul ”Dibawa Gelombang” (Madah Kelana 16). Sangat jelas keterikatan penulis Pujangga Baru itu dengan sistem persajakan Melayu Barus. Berikut adalah cuplikan sajak dimaksud.
Alun membawa bidukku pelahan
Dalam kesunyian
malam waktu
Tidak berpawang tidak berkawan
Entah ke mana aku tak tahu
Jauh di atas bintang kemilau
Seperti sudah berabad-abad
Dengan damai mereka meninjau Kehidupan bumi yang kecil amat
...
Pola sajak yang digunakan oleh Sanusi tersebut ialah
ABAB yang lazim terdapat dalam pantun. Namun, dalam kajian Abdul Hadi, sajak itu lebih
mirip dengan syair. Selain karena
tidak tersirat adanya sampiran dan isi atau pembayang dan maksud pada setiap
baitnya, sajak ”Dibawa Gelombang” adalah seperti syair pada umumnya juga karena
kecenderungannya untuk bercerita secara naratif dan tidak sekadar untuk melukiskan
sesuatu.
Cerita naratif yang disajikan itu serupa dengan syair sufi. Penyair sufi bercerita tentang pengalaman atau perjalanan rohani
dan keadaan jiwa pribadi
untuk mencapai persatuan mistik (unio-mystica)
dengan alam semesta, yang merupakan
keluasan tak bertepi. Dalam hal gerakan sastra ini, Abdul Hadi bersepakat
dengan Teeuw (1994) mengenai pernyataan pengutamaan individualitas
yang diawali/didahului oleh penyair Barus, Hamzah Fansuri, dalam
penciptaan karya sastra yang sangat eksplisit menyebut diri sendiri, antara
lain, dengan kata ganti persona pertama (aku).
Tidak hanya Sanusi Pane, tetapi karya Sutardji Calzoum Bachri juga bercorak sufistik untuk menggambarkan pendakian rohani ke puncak hakikat diri. Hakikat diri manusia, menurut penyair sufi, tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan sandaran keilmuan formal, tetapi juga perlu ditempuh melalui jalan kebenaran Ilahiah. Dalam hal ini, Abdul Hadi mengupas sajak Sutardji Calzoum Bachri yang dinilai paling menarik, yakni sajak ”Sampai”, sebagai berikut.
Rumi menari bersama
Dia
tapi kini di mana
Rumi
Hamzah jumpa Dia di
rumah
tapi kini di mana
Fansuri
Tardji menggapai Dia
di puncak
tapi kini di mana
Tardji
kami tak di mana
mana
kami mengatas
meninggi
kami dekat
...
Tentu
sangat menarik kajian Abdul Hadi yang dalam objek kajiannya juga telah
dimasukkan karya sastra sufi dari Sutardji Calzoum Bachri: pelopor angkatan
1970-an dengan julukan sebagai presiden penyair Indonesia. Kajian ilmiahnya menunjukkan
penelusuran akademis yang amat komprehensif atas DNA sastra bangsa Indonesia melalui
tinjauan hermeneutik kerohanian (tinjauan
ta’wil dalam istilah metodologis dari
Abdul Hadi, 2020: 342) untuk mengetahui sifat dasar kebahasaan dalam karya
sastra, terutama dalam karya Syekh Barus yang kaya akan gagasan “Ketuhanan Yang
Maha Esa”.
Kenangan dan Harapan dari
Barus
Kini,
sang Guru Besar. Prof. Dr. Abdul Hadi W.M. memang sudah tiada, tinggallah
kenangan. Namun, dari nama besarnya, hasil studi Abdul Hadi untuk menelusuri sifat
kehidupan bahasa (persatuan) Indonesia selama empat abad pembentukannya dalam DNA
sastra bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud Kementerian PPN/Bappenas (2023)
tidak akan lekang. Kajian Abdul Hadi, agaknya, bermanfaat ganda guna
memperjelas gambaran arah pembangunan bahasa dalam kebijakan Rancangan
Teknokratik RPJMN 2025—2029. Gambaran arah dimaksud tampak bercabang dua: masa
lalu dan masa depan berkeindonesiaan melalui bahasa dan sastra.
Pertama,
kajian Abdul Hadi sangat bermanfaat untuk mengenang masa lalu bahasa Indonesia
melalui penelusuran DNA sastra bangsa Indonesia. Seturut dengan pandangan Yudi
Latif (dalam komunikasi pribadi, 2023), setiap kenangan adalah bak arus di sungai yang mengalir dari
hulu pada masa lalu. Tanpa berkemampuan mengenang hulu masa lalu itu, manusia
Indonesia yang tak mengerti asal-usulnya ialah ibarat orang yang “memasuki
lorong sunyi kegelapan”. Alih-alih sunyi kegelapan, sepanjang lorong waktu yang telah sukses
ditembus oleh Abdul Hadi untuk meneroka DNA sastra bangsa Indonesia (sejak lima
abad yang lalu) tampak gemerlapnya asal-usul bahasa Indonesia dengan gema sastra
sufi Hamzah Fansuri dari Barus.
Manfaat kedua, yang tak kalah penting dari kekaryaan Abdul Hadi, ialah untuk menyuguhkan harapan atau impian sebagai gelombang cahaya yang memancar ke masa depan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk itu, Yudi Latif berkata bahwa tanpa berkemampuan memimpikan masa depan, manusia Indonesia itu ibarat penjelajah limbung tak tahu pelabuhan mana yang harus dituju. Nah, sekarang—dalam kurun waktu seperempat abad dari abad ke-21 sebagai abad konsolidasi kebahasaan—bahasa Indonesia diharapkan atau diimpikan mampu melambung tinggi hingga berfungsi dalam sifat kemodernannya menjadi bahasa internasional. Dengan kenangan dari Barus, impian itu pun akan lebih mudah diraih.
“Saudaraku,
elang terbang di langit tinggi,” kata Yudi Latif (2023) sembari menyingkap keluhuran
manusia Indonesia sejati dengan sepasang sayap imajinatif: kenangan dan impian. Setinggi apa pun terbangnya, burung elang “tetap bersarang di tanah”.
Seturut dengan perkataan bijak itu, misi penginternasional bahasa (dan sastra)
Indonesia tetap berpijak pada kebijakan kebahasaan untuk
menunjukkan jati diri bangsa Indonesia (Peraturan Pemerintah RI Nomor 57
Tahun 2014: baca Pasal 31 ayat (1)).
Untuk
menunjukkan jati diri yang dasar sifatnya terbawa dalam DNA sastra bangsa
Indonesia, terdapat ungkapan “tanah air bahasa Indonesia” yang merujuk pada
bentangan wilayah kebahasaan dari Merauke (Papua) hingga Sabang (Aceh). Pada
bentangan wilayah berkeindonesiaan ini, Abdul Hadi telah menunjukkan sebuah
titik pijakan berimajinasi demi bahasa persatuan ini, yakni episentrum
peradaban Nusantara di Negeri Melayu Barus. Dari Barus pada masa silam inilah,
telah terpancar cahaya gemerlapnya sastra bangsa Indonesia, sesungguhnya.

Maryanto
Widyabasa Ahli Madya, Badan Bahasa (Penghayat Trigatra Bangun Bahasa)
