Pesantren, Moderasi Beragama, dan Aktivitas Literasi Sastra
Pesantren kini tidak hanya menjadi tempat pendidikan tradisional. Pesantren tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang bersinergi dengan lembaga pendidikan formal pada umumnya, termasuk perguruan tinggi. Dengan sinergi ini, siswa dan mahasiswa juga dapat menjadi santri yang tinggal di pondok pesantren. Dari sinilah kemudian—pada tingkat pendidikan tinggi—tumbuh pesantren mahasiswa (pesma), yaitu pondok pesantren yang sebagian santrinya merupakan mahasiswa aktif di perguruan tinggi yang menjadi mitra pesantren.
Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan formal di Indonesia, memiliki peran yang penting dalam mendorong dan mempromosikan moderasi beragama. Pesantren kini menjadi tempat pendidikan agama Islam yang juga memberikan penekanan pada pendidikan umum secara seimbang. Dalam konteks ini pesantren berusaha memberikan pemahaman agama yang inklusif, mengajarkan nilai-nilai moderasi dan toleransi, serta saling menghormati antarumat beragama.
Moderasi beragama adalah konsep yang mendorong umat beragama untuk mengadopsi sikap tengah, seimbang, dan moderat dalam menjalankan ajaran agama mereka. Moderasi beragama bertujuan untuk meminimalkan konflik antaragama, menghormati perbedaan keyakinan, serta mempromosikan dialog dan kerja sama antarumat beragama. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya menghargai pluralitas dan menghindari ekstremisme serta radikalisme.
Moderasi beragama dalam hal ini dapat dipahami sebagai cara pandang seseorang yang beragama untuk tidak menggunakan kekerasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pengambilan keputusan, cara berpikir, dan ide-ide kehidupan (Hilmy, 2013: 28). Oleh karena itu, kemitraan dan sinergisitas pesantren dengan perguruan tinggi diharapkan makin mempertebal pengaruh lembaga pendidikan Islam dalam fungsi moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama dipahami sebagai cara masyarakat untuk mampu mengontrol keragaman agama sehingga muncul sifat dan perilaku yang harmonis dengan orang lain (Shihab, 2019).
Moderasi Beragama
Istilah moderasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio yang mempunyai arti sedang (tidak lebih dan tidak kurang). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moderasi memiliki dua pengertian, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned (tidak memihak).
Istilah moderasi beragama terbentuk dari dua kata, yakni kata moderasi dan beragama. Moderasi berasal dari kata moderat yang memiliki arti menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem atau kecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Dalam bahasa Arab (Al-Qur’an), moderasi disebut dengan istilah wasathiyah. Istilah ini berasal dari kata al-wasth atau al-wasath, keduanya merupakan bentuk infinitive (mashdar) dari kata kerja wasatha, maka kata al-wasthiyah berdasarkan makna etimologis di atas berarti suatu karakter atau sifat terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrem (Zamimah, 2008).
Menurut Shihab (2004), pada mulanya al-Wasath bermakna segala yang baik yang berada pada posisi di antara dua yang ekstrem. Misalnya, sifat berani (al-saja’ah) adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut. Sifat dermawan merupakan sifat pertengahan antara boros dan kikir. Dengan demikian, orang yang menjadi penengah di antara orang yang berseteru atau bertanding disebut wasith (wasit) yang selalu berada pada posisi tengah dan berlaku adil bagi kedua belah pihak yang berseteru atau bertanding.
Menurut Hanafi (2009), al-wasthiyah secara terminologis berarti moderat, yaitu suatu metode berpikir, berinteraksi, berperilaku yang didasari atas sikap tawazun (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan tradisi masyarakat.
Moderasi agama selama ini di Indonesia dipahami sebagai jalan hidup: pertama, konsep beragama dengan tidak menggunakan kekerasan; kedua, mengimplementasikan nilai-nilai modern dalam beragama; ketiga, berpikir secara rasional untuk memiliki penafsiran dan pemahaman agama; keempat, beragama secara kontekstual sehingga tidak terpaku pada teks; serta kelima, dalam berijtihad mengacu pada Al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman (Hilmy, 2019).
Wacana moderasi beragama di Indonesia dipahami dalam tiga konsep penting, yakni moderasi gerakan, moderasi perbuatan, dan moderasi pemikiran. Konsep itu mengarahkan agar gerakan keagamaan di Indonesia harmonis dengan keberagaman. Tingkah laku diwujudkan dengan tindakan untuk berbuat baik dengan orang yang berbeda agama, suku, atau ras. Sementara itu, pada ranah pemikiran diharapkan bahwa orang beragama dapat berpikir secara rasional dengan pertimbangan kontekstual terhadap problem yang ada.
Moderasi beragama dalam skala nasional juga sangat diperhatikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Dalam hal definisi Kemenag RI menitikberatkan untuk tidak terlalu ekstrem dalam beragama. Sifat ekstrem menurut pemerintah buruk karena ekstrem dasarnya adalah berlebih-lebihan. Bahkan, berlebih-lebihan dalam berbuat baik saja tidak baik (Kemenag RI, 2019).
Contoh gamblang dari definisi tersebut ialah ketika seorang pemeluk agama mengafirkan saudara sesama pemeluk agama yang sama hanya karena berbeda paham keagamaan, organisasi, atau mazhab. Seseorang juga dapat dikatakan berlebihan dalam beragama ketika sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina simbol suci agama tertentu (Kemenag RI, 2019).
Prinsip Beragama dan Implementasi Nilai Moderat di Pesantren
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimanakah prinsip beragama secara moderat? Ada dua prinsip: adil dan berimbang. Adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakan dengan baik dan secepat mungkin. Sementara itu, berimbang ada pada posisi tengah, tidak condong kepada salah satu sisi. Dalam beragama, misalnya, orang tidak hanya patuh kepada Tuhan dalam perkara syariat, tetapi juga perkara muamalah, ibadah kemanusiaan (Kemenag RI, 2019).
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya penguatan moderasi agama. Pada lingkup aparatur sipil negara (ASN), misalnya, pemerintah mengeluarkan aturan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil. Aturan ini diterbitkan untuk membentuk ASN Kementerian Agama yang memiliki sudut pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat serta menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama.
Moderasi beragama harus diwujudkan ke berbagai lini, tidak hanya di tingkat elit. Pada wilayah akar rumput darurat intoleransi masih cukup terlihat. Terjadi banyak peristiwa yang mencederai kemanusiaan karena terdapat perbedaan pemahaman atau mazhab, bahkan tidak jarang dapat timbul polarisasi politik.
Moderasi berkaitan erat dengan budaya atau tradisi. Catatan penting dari terbentuknya Nusantara adalah akar akulturasi budaya yang sangat cair, bahkan dengan warga asing. Artinya, Nusantara adalah tempat orang-orang dari berbagai suku, adat, ras dan budaya berbaur dan menjalin komunikasi. Moderasi beragama harus memunculkan sikap demokratis pada berbagai wilayah kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, agama, politik, hingga hubungan internasional (Muhidin, et al., 2021; Nashir, 2015).
Dengan demikian, moderasi beragama adalah ideologi yang berupa pola perilaku kehidupan beragama untuk mengambil posisi di tengah sehingga seseorang dapat berperilaku adil dan tidak ekstrem hanya berdasarkan interpretasi tekstual saja. Secara prinsip, pandangan mengenai moderasi beragama diwujudkan dalam sifat yang adil dan berimbang. Maksud dari sifat itu adalah agar manusia dalam beragama selalu menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu sehingga kontekstual dengan zaman. Selain itu, manusia juga harus seimbang antara jasmani dan rohani agar antara dunia dan akhirat dapat tercapai dengan baik. Konsep itu mengarahkan agar manusia memiliki jalan hidup yang tertata dan kontesktual.
Sebagai lembaga pendidikan, pesantren tercatat sebagai yang tertua di Indonesia. Langgar dan surau menjadi tempat belajar kitab (ngaji kitab) secara rutin. Proses pembelajarannya sederhana. Kiai membacakan dan memberi makna kitab, sementara santri mendengarkan, tak sedikit yang memberi catatan pada kitab. Selain fiqh dan ushul fiqh, tasawuf juga diajarkan oleh kiai.
Akan tetapi, pesantren dewasa ini telah berkembang pesat. Nuansa modern dipadukan dengan pendidikan salaf (konvensional). Transformasi pada bidang epistemologi dan metodologi sudah jamak dilakukan oleh pesantren. Pesantren Tebuireng Jombang menjadi salah satu inisiator. Banyak kurikulum modern yang dimasukkan ke dalam pembelajaran, seperti pelajaran Bahasa Inggris, Manajemen, Ilmu Sosial, dan Wawasan Kenegaraan, apalagi saat ini banyak universitas. Selain Tebuireng, Pesantren Darul ‘Ulum Peterongan Jombang juga melakukan misi yang sama dengan berdirinya Universitas Darul ‘Ulum (Undar) (Mukhammad Abdullah, 2019; Akhmadi, 2019; Subchi, et al., 2022).
Salah satu perkembangan pesantren yang pesat ialah wawasan kebangsaan dalam bentuk moderasi beragama. Moderasi selalu dikaitkan dengan paradigma pesantren terhadap kehidupan sosial keagamaan, baik filosofis maupun praktik (Dhofier, 2011; Muqoyyidin, 2014). Moderasi agama di pesantren dilandasi konsep tawasut dengan pelbagai konsep yang indah dan khas pada wilayah akidah, ibadah dan akhlak, serta hubungan sesama manusia (Khotimah, 2020; Nurdin & Syahrotin Naqqiyah, 2019).
Pondok Pesantren Al-Falah Cianjur, misalnya, menekankan sikap moderasi pada akhlak para santri. Hal itu merupakan wujud elaborasi keilmuan yang mereka serap dari kiai. Apresiasi dan toleransi menjadi sikap yang harus tumbuh di civitas academica Pesantren Al-Falah. Kiai tidak pernah menyalahkan santrinya apabila mereka belum memahami ilmu. Prinsip moderat yang dipegang ialah bahwa menuntut ilmu itu ibadah; menyampaikan ilmu itu dakwah; dan mengulang-ulang ilmu adalah zikir.
Setidaknya ada tiga faktor yang menjadikan pesantren berfungsi sentral dalam mewujudkan moderasi: pertama, konsep wasatiyah; kedua, muatan lokal yang kental; dan ketiga, pesantren serta kiai memiliki pengaruh kuat pada wilayah sosial, agama, dan budaya pada masyarakat. Muatan lokal biasanya diiringi dengan basis ideologi ahlussunah wal jamaah Nahdlatul Ulama (NU). Bahkan, Madura populer dengan anekdot “orang Madura agamanya NU” (Dera Nugraha, 2021; Syarif, Zainuddin dan Hannan, 2020).
Senada dengan Pesantren Al-Falah Cianjur, Pesantren Sukorejo Situbondo asuhan K.H. Azaim Ibrahimy bin alm. K.H. As’ad Syamsul Arifin, melalui ma’had aly-nya, juga mensyiarkan moderasi beragama. Ciri moderasi yang muncul pertama kali ialah terbitnya buletin Tanwirul Afkar. Buletin tersebut eksis sejak 1997. Isu sensitif yang pernah dalam buletin itu ialah perayaan hari Valentin dan hubungan sosial bersama nonmuslim. Menurut ma’had aly, perayaan hari Valentin tidak melanggar syariat karena bukan ritual keagamaan, sebagaimana menghargai hak kemanusiaan nonmuslim. Corak ijtihad Ma’had Aly Situbondo sangat moderat karena didasari oleh konsep revitalisasi fiqh, diversifikasi teks (teks tandingan), dan perluasan wilayah takwil (mendudukkan teks pada konteksnya) (Aziz, 2020; Dakir dan Anwar, 2019).
Moderasi beragama di pesantren selalu berkaitan dengan realitas sosial. Oleh karena itu, kedua pesantren di atas menunjukkan bahwa ada kohesi antara tauhid, fiqh, tradisi, dan akhlak yang moderat sebagai model. Nilai Ilahiah dan insani dalam pendidikan pesantren, sebagaimana disebut Harun Nasution, harus kaffah atau menyeluruh (Awwaliyah, 2019; Dakir dan Anwar, 2019). Artinya, kedua pesantren di atas menjadi representasi kemenyeluruhan tersebut.
Sebagai perangkat pendidikan, kurikulum moderasi agama harus dipertahankan dengan manajemen yang baik. Pada Pesantren Al’ulum Wal Athaf Madura, misalnya, manajemen pesantren berkaitan dengan moderasi, yang dimulai dari perencanaan yang matang. Perencanaan ini terwujud dalam program pendirian pendidikan formal, penentuan arah program, hingga penyusunan materi pembelajaran. Pada setiap jenjang kitab yang dipelajari berbeda-beda. Dalam ilmu akhlak, misalnya, jenjang ibtidaiah mempelajari Ta’limul Mutaalim, jenjang sanawiah mengkaji ‘Idhotun Nasyiin, dan jenjang aliah mendaras kitab Adabul ‘Alim wa Muta’alim. Dari ketiga kitab itulah rujukan sikap moderat tumbuh pada diri santri dan pengasuh (Soleh dan Hasanah, 2021).
Implementasi nilai moderat di pesantren secara keseluruhan berdampak pada dua hal berikut: pertama, perkembangan pesantren; dan kedua, masyarakat sekitar pesantren. Masyarakat tidak hanya termotivasi pada wilayah teologis, tetapi juga sosiologis (Khojir, 2020). Kenyataan ini menguatkan argumen bahwa ahlussunah wal jamaah terkait dengan moderasi beragama. Artinya, sebagaimana berpegang pada asas tunggal Pancasila, pesantren sudah seyogianya mengelaborasi Al-Qur’an, hadis, ijmak ulama, dan konstitusi bangsa Indonesia sebagai model moderasi beragama.
Penutup
Praktik moderasi beragama di pesantren merupakan salah satu kajian yang saat ini penting untuk dilakukan secara lintas disiplin ilmu. Pesantren memiliki tradisi intelektual yang sangat kuat, terutama dalam hal aktivitas literasi sastra. Sejak awal berdirinya, pesantren telah memiliki tradisi literasi teks yang sangat bagus, yaitu kajian kitab kuning, tafsir atau interpretasi teks, dan sebagainya. Sistem pendidikan pesantren juga identik dengan aktivitas sastra, seperti singiran, kidung, syair, atau nadam. Dalam konteks kekinian, aktivitas tersebut terus berkembang. Santri di pondok pesantren tidak hanya mengkaji kitab kuning sebagai bagian dari literasi teks, tetapi juga sudah mulai mengembangkan aktivitas literasi sastra Indonesia sebagai bagian dari tradisi intelektual. Aktivitas ini menjadi salah satu alternatif sekaligus pengembangan moderasi beragama di pesantren.
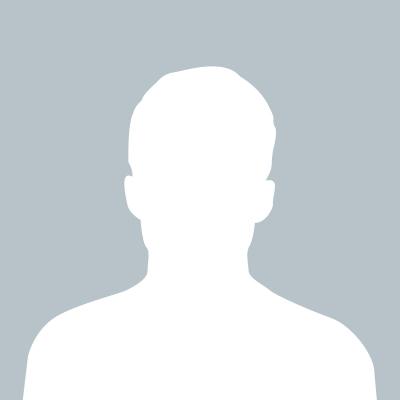
Abdul Wachid B.S.
Guru Besar/Profesor Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan sempat jadi Ketua Senat (periode 2019-2023)
