Tradisi Sastra (di) Pesantren
Pesantren sebagai pusat pendidikan
Islam tradisional di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter
santri dan mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang toleran dan
inklusif. Kurikulum pendidikan di pesantren menekankan pembentukan karakter
melalui tradisi bersastra. Eksistensi syiir dan nadhom menjadi
indikasi bahwa nuansa sastra cukup dominan di pesantren.
Sastra selalu dikaitkan dengan bahasa. Padahal, sastra juga sering mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan agama, sosial, dan budaya. Di pesantren misalnya, sastra diposisikan secara kreatif. Sastra sebagaimana santri adalah dua entitas yang secara bersamaan dapat dimaknai sebagai keindahan (Burhanudin, 2017; Muzakka, 1999).
Relevansi Sastra dan Agama
Sebelum dibahas kaitan sastra dengan
moderasi agama secara lebih lanjut, akan dibahas terlebih dahulu relevansi sastra dan agama (dalam hal ini pesantren).
Sesungguhnya, dalam konteks kurikulum pembelajaran di pesantren, tidak ada sastra di dalamnya, bahkan sejak
pesantren pertama berdiri di Tegalsari pada abad ke-17. Akan tetapi, pada saat
itu Pesantren Tegalsari dan pesantren lain pada umumnya menjadi tempat
berkumpulnya para pujangga yang menghasilkan karya sastra besar, seperti
Yasadipura 1, Yasadipura 2, dan Ranggawarsita. Mereka juga merupakan representasi
dari keraton. Artinya, pesantren, sastra, dan keraton sudah memiliki hubungan yang berkait-kelindan sejak mula (Irawan M.N.,
2018; Tabroni, 2019).
Ciri khas pesantren abad ini adalah pengadaptasian karya berupa cerita rakyat Nusantara, Timur Tengah, ataupun India yang menjadi cita rasa Islam Nusantara (Indonesia). Pengadaptasian ini mempunyai tujuan sosial-keagamaan.
Karya yang diteliti, misalnya,
ialah Serat Cebolek, Serat Sasanasunu, Serat Kalatida. Karya tersebut
adalah sastra kaum santri pada abad ke-17 sampai dengan ke-19 yang diproduksi
dengan lokus santri pesisir utara Jawa (Baso, 2012).
Diambil sebagai contoh Serat
Cebolek. Ajaran mistik dan ajaran moral dalam serat tersebut berjalan
serasi. Secara garis besar, Serat Cebolek terdiri atas dua bagian, yaitu berisi tentang perdebatan atara H. Pinang, penghulu Batang, dan
K.H.A. Rifa’I serta tentang perdebatan
antara Kiai Khotib Anom dan Syekh Ahmad
Al-Mutamakin dari Cebolek. Serat ini, menurut Yasadipura 1, menggambarkan
keahlian ulama Kudus dalam membaca dan menafsirkan naskah Jawa Kuno di hadapan
priayi Keraton Surakarta (ulama birokrat) (Siti Nur Laili, 2020; Tabroni,
2019).
Selain Serat Cebolek, ada
juga Serat Sasanasunu. Serat itu berisi mengenai empat kepribadian untuk menjadi manusia
ideal dari
segi agama: priayi, santri,
petani, dan saudagar. Keempatnya dijadikan oleh
Yasadipura 2 sebagai simbol perwatakan. Priayi digunakan untuk menggambarkan
orang beradab. Santri digunakan untuk menggambarkan sifat jujur, suci, dan pemaaf. Petani digunakan untuk menggambarkan
sifat orang yang memiliki ketekunan. Saudagar atau pedagang digunakan untuk
melukiskan orang yang memiliki sifat perhitungan, hemat, dan hati-hati (Wardhana, 2014).
Sejarah di atas menunjukkan bahwa kaitan antara sastra dan agama (pesantren) bersifat maknawi. Kolaborasi antara pesantren, pujangga, dan keraton dalam membentuk masyarakat yang beradab, jujur, tekun, dan hati-hati berangkat dari ajaran yang terdapat di Serat Cebolek dan Serat Sasanasunu. Dimensi tasawuf sangat mendominasi. Oleh karena itu, pesantren sampai dengan detik ini mengetengahkan tasawuf (ilmu batin) menjadi ilmu yang pokok, selain fikih dan tauhid (Mansur, 1999).
Budaya Literasi Berkembang Pesat di Kalangan Ulama
Pesantren
Semenjak masyarakat Nusantara
mengenal Islam, mencuat kebutuhan akan pengetahuan Islam. Kebutuhan itu mengarahkan pada tradisi baca-tulis keilmuan Islam (Maskur 2019). Hal itu seperti yang terjadi di Surakarta, yaitu proses transmisi keilmuan didukung oleh sultan. Sementara itu, dalam pelaksanaannya diperbantukan kaum santri dengan menghasilkan 145 teks. Teks-teks tersebut sarat akan kesusastraan
Islam, di antaranya, ialah serat, suluk, babad, sejarah, dan primbon. Di Surakarta juga terdapat santri
yang mumpuni dalam teks kesastraan, yakni Ronggowarsito. Jika berbicara ihwal Ronggowarsito, pembaca akan teringat
kakeknya, yakni Kiai Amongraga. Kiai Amongraga adalah pengarang dari Serat Centini. Serat Centini
menghimpun segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa agar tak punah dan
tetap lestari sepanjang waktu.
Di pesantren, para santri kerap
melakukan tradisi berseni dan bersastra yang hingga hari ini masih
dipertahankan. Para santri di pesantren
mengkaji kitab-kitab keagamaan yang berupa
kitab klasik atau disebut kitab kuning. Jika ditinjau dari perspektif wadah, sastra pesantren
mewujud, sebagian besar, dalam bentuk kitab-kitab berbahasa Arab dengan
berbagai macam corak (Sungaidi, 2020). Kitab-kitab di pesantren memuat isi:
gramatika bahasa Arab, puisi Arab, prosodi Arab, tafsir, hadis, tarikh, dan
tasawuf. Semua ilmu tersebut dipelajari oleh para santri di pesantren. Melalui
pembelajaran dari kitab-kitab kuning, pada diri para santri terbentuk sikap yang moderat dan insklusif dalam menghadapi
realitas sosial-budaya sehingga masyarakat pesantren dapat menyumbangkan
kecerdasan spiritual melalui sarana sastra.
Keberadaan pondok pesantren di Nusantara
telah membentuk sistem pembelajaran mengenai pengetahuan agama yang
dikontekstualisasikan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran itu juga
tidak jarang menjadikan karya sastra sebagai usaha untuk menyampaikan
nilai-nilai Islam. Hal itu sebagaimana
yang dikatakan oleh Abdul Hadi W.M. (2004), “Dalam sejarah pemikiran
Melayu-Nusantara bukan saja karena gagasan tasawufnya, melainkan juga karena karangan dan puisi-puisi yang
mencerminkan semangat penggambaran spiritual.” Oleh karena itu, dari pondok pesantren muncul syekh
dan beberapa kiai yang menulis karya sastra sebagai pengetahuan dan wawasan
mereka terhadap agama Islam.
Pentingnya literasi sastra bagi santri di pondok pesantren mengingatkan kita akan salah satu karya Amir Hamzah yang di dalamnya
memuat nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis.
Kemudian, ada pula karya suluk dari
Sunan Bonang yang dijadikan sebagai media oleh orang Jawa untuk belajar Islam. Berkaitan dengan hal itu, Subur mengatakan bahwa proses pendidikan yang terjadi di dalam
pendidikan Islam ialah melalui
karya sastra yang disajikan melalui kisah (Subur, 2014). Hal itu tak dapat
dipisahkan mengingat sejarah dari agama Islam diliputi banyak hikmah. Bahkan,
seandainya Al-Qur’an dikupas seluruh isinya, kebanyakan dari isinya mengungkap
kisah-kisah kehidupan yang berguna sebagai pembelajaran bagi seluruh manusia.
Melalui karya sastra, kisah dari manusia itu dapat ditransmisikan oleh pembaca untuk memetik hikmah yang
tersembunyi di dalamnya.
Sastra dengan segala ekspresinya
merupakan pencerminan dari kehidupan manusia, sedangkan segala permasalahan
yang ada pada manusia merupakan ilham bagi pengarang untuk diungkapkan melalui
karya sastra (Achmad, 2014). Pengalaman spiritual dari yang dialami oleh
seseorang berdasarkan hubungan dengan Tuhan akan menjadi pengetahuan. Pengetahuan
tersebut dapat memberikan pencerahan kepada orang yang membaca untuk turut
mendalami kehidupan. Dalam perspektif pondok pesantren, kisah dari karya sastra
menjadi sebuah metode untuk menyampaikan pesan, bahkan ajaran. Segala preseden
yang tersaji di dalam karya
sastra
memiliki unsur konstruksi yang
membangun kesadaran para santri yang membentuk kesadaran jiwa. Tak hanya itu,
kisah juga dapat memengaruhi emosi kejiwaan dalam sebuah amanat dan
menginspirasi pembaca (Novi, 2018).
Secara sederhana, para santri di
pesantren sangat pekat dengan budaya literasi. Istilah literasi pada
umumnya mengacu pada keterampilan membaca dan menulis. Hal itu
bermakna bahwa seorang literat adalah dia yang telah menguasai
keterampilan membaca serta menulis dalam suatu bahasa. Namun, pada umumnya
keterampilan membaca seseorang itu lebih baik daripada kemampuan menulisnya. Bahkan,
kemampuan atau keterampilan berbahasa lainnya yang mendahului kedua
keterampilan tersebut dari sudut kemudahannya dan penguasaannya adalah
kemampuan menyimak dan berbicara. Literasi berasal dari bahasa Latin literatus yang berarti ‘a learned person’ atau ‘orang yang belajar’. Pada abad pertengahan, seorang literatus
adalah orang yang membaca, menulis, dan bercakap-cakap dalam bahasa Latin. Lantas, kemampuan literasi tak
hanya perihal membaca, tetapi juga
menulis (Syaiful, 2021).
Sebagai proses berpikir, membaca berkaitan dengan aktivitas pengenalan
kata, pemahaman literal, intrepretasi, pembacaan kritis, dan pemahaman kreatif. Sementara itu, menulis
ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan
suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca
lambang-lambang grafik tersebut karena
di dalamnya terkandung pesan yang dibawa
penulis (Amin, 2018). Pesan yang dibawa oleh penulis melalui gambaran huruf-huruf itu disebut karangan. Karangan
sebagai ekspresi pikiran, gagasan, pendapat, dan pengalaman disusun secara sistematis dan logis.
Aktivitas membaca dan menulis merupakan hal yang berkait kelindan. Seseorang yang menulis tentulah harus
melewati proses membaca. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang dalam
membaca dan menulis.
Secara umum, preseden kemunculan literasi dalam Islam dapat dilihat dari cara umat Islam menulis Al-Qur’an pada zaman Nabi Muhammad saw. meskipun tradisi baca tulis belum menjadi budaya di
kalangan bangsa Arab. Tradisi masyarakat Arab kala itu masih didominasi tradisi
lisan (Ja’far, 2022). Masyarakat Arab memiliki tradisi menghafalkan syair-syair dan puisi, termasuk silsilah atau garis-garis
keturunan. Sementara itu, apabila kita menengok tradisi literasi umat Islam
Indonesia, khususnya di kalangan pesantren, hal itu sudah mengakar kuat melalui kitab kuning (Muzakka,
2020).
Secara umum, kitab kuning dipahami sebagai kitab-kitab
keagamaan berbahasa Arab dan beraksara Arab yang dihasilkan oleh para ulama
dan para pemikir muslim lainnya,
terutama dari Timur Tengah. Kitab kuning sebagai kitab klasik berbahasa Arab
telah dikenal dan dipelajari pada abad ke-16. Kitab kuning tak hanya berbahasa
Arab, tetapi juga ada yang berbahasa daerah, seperti Melayu dan Jawa, tetapi dengan aksara Arab (Pegon). Argumen yang dijadikan
dasar ialah adanya naskah di Indonesia yang berbahasa
Arab, Melayu, Jawa, Sunda, dan
sebagainya.
Kitab kuning memiliki peran yang
penting karena itu dijadikan
sebagai text book, references, dan
kurikulum dalam sistem pendidikan pesantren (Resti, 2019). Selain sebagai
pedoman tata cara keberagamaan, kitab
kuning difungsikan juga oleh kalangan pesantren sebagai referensi dan bahan kurikulum dalam sistem pendidikan pesantren.
Kitab kuning baru muncul di
Indonesia pada abad ke-17. Kitab Kuning,
seperti Taqrib karya Abu Suja’ Al-Isfahani (w. 593H/1196 M) dan Al-Muharrar karya Abu
Qashim Al-Rafi’ (w. 623H/1226 M) dibawa oleh para murid Jawi yang belajar di
Haramain ketika kembali pulang ke tanah air (Ulfatun, 2015). Pada abad ke-17
ini makin banyak pelajar Jawi yang belajar di Tanah Suci.
Setelah menamatkan pelajarannya, kemudian kembali ke tanah air, mereka membawa
kitab-kitab yang dikajinya dan kemudian menyebarkannya ke lingkungan yang
mengerti bahasa Arab.
Pada abad ke-1 s.d. ke-2 Hijriah, kitab kuning menemukan momentumnya ketika
dijadikan sebagai materi pokok pengajaran di pondok pesantren, munas, dan
istilah lainnya. Kondisi itu diperkuat dengan adanya pondok pesantren yang
kukuh menganut sistem pengajaran dengan menggunakan kitab kuning serta enggan menggunakan
literatur yang berasal dari bangsa kolonial. Dari sinilah awal mula kitab
kuning menjadi rujukan pokok dari kurikulum di pondok pesantren. Budaya
keilmuan dalam sistem pesantren umumnya berkembang dalam tradisi lisan
(Lailatul, 2019). Hal itu dapat
dibuktikan dengan sistem pengajaran yang dipakai yang berupa sorogan dan hafalan. Selain tradisi lisan,
budaya intelektual orang pesantren pada masa
lampau ialah tradisi tulis. Tradisi
tulis terbukti
dengan dihasilkannya karya-karya autentik yang ditulis oleh para ulama.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa budaya literasi berkembang pesat di
kalangan ulama-ulama. Namun, jika kita melihat kondisi sekarang ini, bidang
kepenulisan masih didominasi oleh kaum intelektual dari kalangan nonpesantren.
Masih jarang sekali karya yang dihasilkan oleh santri pondok pesantren yang mengisi rak-rak buku di
perpustakaan dan toko-toko buku, bahkan sangat langka (Syarif Z, 2020). Selain
itu, artikel juga masih jarang mengingat rendahnya penguatan literasi dan
kompetensi kepenulisan di pesantren. Padahal, sesungguhnya pesantren sudah
sangat ditunjang oleh sistem pembelajaran yang menggunakan media kitab-kitab
klasik sebagai sumber rujukan utama. Para santri juga dituntut untuk dapat
membaca dan menghafal teks-teks
berbahasa Arab tersebut secara intensif melalui kajian literatur dalam bidang
ilmu agama, seperti fikih, tasawuf, tafsir, ilmu linguistik, dan
gramatika bahasa Arab.
Lingkungan pesantren sangat didukung dengan situasi yang kondusif dalam hal penanaman nilai-nilai (Djihadah, 2022). Dalam konteks ini sesungguhnya santri mempunyai potensi yang cukup kuat untuk menuangkan gagasannya di bidang-bidang keilmuan yang dikaji di pesantren melalui bimbingan seorang kiai. Sayangnya, potensi tersebut tidak serta-merta diikuti dengan motivasi yang kuat untuk menulis dan menuangkan ide-idenya dalam bentuk suatu karya tulis. Para santri di pesantren banyak bersinggungan dengan syiir, puisi klasik, hingga kesusastraan Arab. Oleh karena itu, pesantren berkait kelindan dengan ajaran Islam, yaitu berpatokan pada tradisi sastra dengan menjadikan religiositas sebagai materi utama dan dengan puncak kemanusiaan sebagai tujuan hidup (Juhairiyah, 2022).
Tradisi Sastra
Sastra dalam pesantren difungsikan
sebagai hiburan dan pendidikan spiritual. Hal itu sebagaimana
pendapat Muzakkar yang menyatakan
bahwa sastra sangat efektif sebagai media pendidikan dan pengajaran nilai
humanis dan religius. Ekspresi nilai-nilai humanis dan religius dalam
simulasi-simulasi terapan pengetahuan Islam sangatlah kompleks, khususnya dalam produk-produk kesusastraan di lingkungan pesantren. Sementara itu,
fungsi spiritual dalam sastra merupakan ekspresi penghambaan diri. Tradisi
sastra di pesantren sangatlah mudah kita temukan melalui karya-karya ulama
klasik yang diajarkan di pesantren-pesantren. Aqidatul Awam karya Syekh
Ahmad Marzuki al-Maliki, misalnya. Meski tergolong kitab yang berisi
ajaran-ajaran tauhid, kitab itu disampaikan dengan gaya nazam (puisi). ‘Iqdul Jawahir karya Syekh
Ja’far al-Barzanji bahkan menjadi kitab yang begitu sering dibaca di berbagai
kegiatan (Syamsul, 2020). Sementara itu, Al-Hikam karya Ibn Athaillah Assakandary serta
hizib-hizib (doa/wirid) Imam Syafi’I dan Syekh Abi Hasan
As-Syadzily juga dapat digolongkan sebagai bagian dari karya sastra yang
dilahirkan ulama klasik (Fitriyah, 2019).
Sastra di dalam pesantren begitu
lekat sehingga ada istilah berupa sastra pesantren atau karya sastra santri, kiai, dan yang mempunyai
silsilah sosial/intelektual dengan pesantren yang bertema kesantrian dan kepesantrenan dengan membawa
semangat kesantrian (religiusitas), baik secara langsung maupun tidak langsung
(Rosyid, 2019).
Tradisi sastra di pesantren sudah berlangsung sedari pesantren itu ada. Masyarakat Indonesia mengingat tokoh besar yang dikenal sebagai pelopor sastra Melayu, yakni Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah tokoh besar yang dilahirkan dari pusat pendidikan Islam (tradisional) pertama di Barus, Aceh yang kemudian menjadi cikal bakal pesantren sekarang ini. Kegiatan literasi di pesantren telah menjadi bersastra yang mengandung tradisi intelektual di lingkungan pesantren. Ada banyak sekali karya-karya para alim ulama yang menulis kitab/karya tulis dengan gaya sastra (Dedi, 2018).
Penutup
Jika
berbicara
tentang sastra, kita akan dihadapkan dengan suatu karya tulis yang memiliki definisi yang
berbeda. Di antara definisi-definisi tersebut akan muncul sebuah simpulan
bahwa sebuah
karya tulis dapat dikelompokkan sebagai karya sastra apabila memenuhi
unsur-unsur tertentu (Thobroni, 2019). Jenis karya sastra keagamaan
juga meliputi novel, cerpen, puisi,
dan drama. Seiring berjalannya waktu, jenis karya sastra makin beragam seturut
maraknya perkembangan
media
sosial dan teknologi informasi. Selain jenis yang berdasarkan bentuk dan
isinya, sastra juga dapat dibedakan berdasarkan tempat karya sastra itu
berkembang dan hidup, seperti sastra pesantren. Kekhasan sastra pesantren, di antaranya,
ialah karena
adanya kekuatan roh transenden yang khas pula. Menurut Gus Dur, ada dua
definisi dari sastra pesantren, yaitu pertama, karya-karya sastra yang
mengeksplorasi kebiasaan-kebiasaan di pesantren dan kedua, adanya corak psikologi
pesantren dengan struktur agama (warna religius yang kuat).***
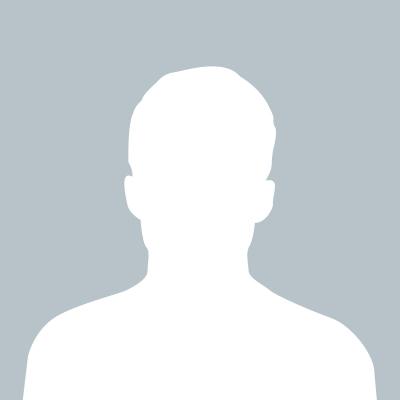
Abdul Wachid B.S.
Penulis adalah seorang penyair dan guru besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto
