Intelektualitas Sastra Cermin Manifestasi Bahasa
Abstrak
Sastra masuk
kurikulum, meski ini bukan hal yang baru, tentu perlu direspons positif. Sejatinya
karya-karya sastra tidak hanya sekadar dibaca, tetapi harus mampu memberikan
kontribusi besar terutama dalam membentuk karakter dan perilaku positif. Sastra
yang memiliki dimensi seni, seharusnya memunculkan paradigma keilmuan, baik
terhadap pengarangnya maupun peminatnya (pembacanya).
Kedua aspek ini, seni dan keilmuan, harus
saling berhubungan dan bersinergi, walaupunmemang ada problem dasar yang sering
tidak disadari oleh pengarangnya. Ia menjual karyanya ke pasar (pembaca) hanya
berorientasi kepada pemuasan individu. Ini tentu tidak akan mampu mengakomodasi
sastra masuk kurikulum. Sesuatu yang wajar jika kemudian pasar pembaca menjadi
ambivalen dan kemudian menjadi polemik.
Seorang ahli
bahasa berkebangsaan Swiss, Ferdinand de Saussure, menyatakan bahasa memberikan bukti terbaik bahwa hukum
yang diterima oleh suatu komunitas bukan aturan yang disetujui secara bebas
oleh semua orang. Ini berarti bahasa menjadi penengah dari
perbedaan-perbedaan secara sosial untuk merumuskan tujuan atau maksud kepada
semua orang. Bahasa menjadi manifestasi dalam interaksi apa pun yang gunanya mengukur
capaian maksud atau tujuan.
Kemajuan
teknologi yang merupakan ekses dari perubahan peradaban tentu memiliki dampak pada
prinsip-prinsip kebahasaan. Dalam kajian linguistik modern salah satu pelopornya adalah Ferdinand de
Saussure. Pemikiran tentang linguistik modern telah disampaikan dalam bukunya
yang berjudul Course de Linguistique
Generale (1916).
Keadaan bahasa pada abadyang berubah secara cepat dan
dianggap memasuki pascamodern ini secara
implisit sudah terjangkau oleh pemikiran para pakar terdahulu. Lalu, bagaimana
ruang kreatif sastra untuk menghadapi perubahan ini? Jawabannya dengan cara
menjadikan sastra sebagai ruang intelektual dalam menghadapi tantangan kemajuan ilmu dan
teknologi modern serta menguasai informasi merupakan syarat mutlak.
Realisme Sastra
Sedikit
ulasan untuk mengenang sejarah sastra, khususnya dalam perjalanan sastra
Indonesia, bahwa sastra pun mengalami pergantian yang disebut sebagai fase
sejarah sastra. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angkatan bagi penyair, yang
kemudian dalam realitas sastraberkembang
melalui aliran atau genre.
Dalam
persaingan karya sastra di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi, perabaan makna bahasa menjadi sebuah tantangan peradaban maju, baik
dalam era modern maupun pascamodern. Penguasaan bahasa melalui sumber-sumber
literasi yang ada tentu akan menghasilkan kematangan dalam karya-karya sastra.Sayangnya,
dalam gerakan penguatan kesastraan tidak ada konvensi (kesepakatan) untuk
menetapkan sebuah indikator bagi karya-karya sastra. Sastra cenderung
melahirkan cara dan jalannya masing-masing karena munculnya pemikiran-pemikiran
baru. Di sini, pemikiran realis sangat kuat memberi pengaruh dalam populasi
karya-karya sastra.
Realitas
sosial yang dilakukan dengan pendekatan imajinatif dan dituangkan dalam
perspektif karya sastra adalah rentetan peristiwa yang melahirkan kematangan
sastra. Sebagai sebuah disiplin ilmu, sastra berkembang dalam prinsip-prinsip
moderat yang mengikuti arah zaman. Oleh karena itu, pada masa silam ada batasan
masa yang menerangkan tentang sejarah sastra.
Beberapa
tahun ini sastra bergeser secara alamiah dalam dinamika masa yang tidak lagi hanya
dihasilkan oleh seniman sastra berlatar belakang akademisi. Ada beberapa
momentum yang memunculkan sebuah paradigma baru, khususnya penulis fiksi. Ada
banyak karya bagus terlahir dari pegiat sastra melalui seleksi alam atau belajar
sastra secara autodidak. Ini mengingatkan kita pada Ajip Rosidi, Chairil Anwar,
atau yang lain.
Para pegiat
sastra atau seniman sastra kini tidak lagi mengandalkan disiplin ilmu secara
didaktis. Tak terhitung lagi, betapa banyak pegiat sastra atau seniman sastra
melahirkan karya-karya bagus dan berkualitas. Artinya, perubahan ini disebabkan
kematangan sastra secara individu oleh pola pikir penulis yang lebih
berorientasi pada sebuah intelektualitas. Hingga sebuah karya sastra yang bagus dan
berkualitas adalah olahan penulis sastra atau penulis fiksi yang memanfaatkan
sumber-sumber ide dari objektivitas pemikiran, bukan hanya olahan subjektivitas
pemikiran yang terkesan intelektual.
Bagai membaca
tembok yang tak berwarna, sastra itu adalah penjara pemikiran yang penuh
pergolakan. Sastra memiliki warna untuk mengukir kehidupan sosial. Akan tetapi,
jika kita bicara tentang sastra, harus juga memadukan unsur literasi, bahasa,
dan budaya. Ini adalah satu-kesatuan yang sulit untuk dipisahkan satu sama lainnya.
Hal ini kadang diterjemahkan sebagai karakter aliran sastra oleh beberapa
pegiat sastra.
Kemampuan
dalam mengolah seni bahasa pada karya sastra memunculkan konsep-konsep idealis sehingga
melahirkan beberapa perbedaan karakter. Konsep sastra menggambarkan sebuah
realisme yang terkadang menabrak kaidah bahasa (konsep gramatikal). Hal ini diebabkan
karya sastra yang menjadi karya fiksi acapkali dianalogikan sebagai gerakan
seni.
Tanpa sadar,
era modern dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi telah memacu para
pegiat sastra dan seniman sastra untuk mengangkat nilai-nilai kreativitas
sastra ke dimensi ruang yang lebih tinggi. Sebagai contoh, karya-karya novel
yang diangkat dan diedarkan secara luas banyak ditulis oleh novelis yang tidak
mengenyam pendidikan sastra secara didaktis. Misalnya, Habiburrahman El Shirazy, Henry Tanjung, dan lain-lain.
Dalam
beberapa kasus, para penulis cerpen, puisi, dan fiksi lainnya, yang saat ini
berkiprah di kehidupan nyata sastra, rata-rata bukan dari kalangan yang berlatar
belakang sastra akademik. Rata-rata hanya mengandalkan olah rasa dan pikiran
yang kemudian memberikan nilai dan simpulan dalam kekuatan sastrawi. Pada akhirnya
diyakini sebagai teori-teori penulisan karya fiksi.
Sebagaimana kita melihat dan membaca secara sederhana, munculnya gerakan-gerakan seni, termasuk seni sastra dalam bentuk kelompok atau komunitas, tidak terlepas dari keberadaan tradisi sastra itu sendiri. Meski terkesan pragmatis, pegiat atau pelaku sastra bisa dikatakan juga sebagai penjaga tradisi bahasa, tetapi lebih terkesan sebagai penggalan-penggalan tradisi sejarah sastra yang hanya berorientasi ke depan. Karya sastra dihasilkandengan jalan pintas yang bertujuan melahirkan sebuah naskah atau karya yang dengan cepat dijamah dan disentuh oleh pembaca atau audiens. Karena ruang kreatif sastra yang begitu luas (ruang digital), sastra sering hanya dimanfaatkan untuk identifikasi sosial, seperti pencitraan diri.
Edukasi dan Intelektual
Ruang digital
yang seyogianya juga sebagai medium bagi pembelajaran dan edukasi bagi para
pelaku dan pegiat sastra memunculkan fakta-fakta baru bahwa siapa saja bisa mencapai
tujuan, seperti menjadi penyair, sastrawan cukup dengan menguasai teknologi
digital. Ruang kreatif digital bagai bola liar yang terkadang menabrak
keterbatasan masyarakat dalam memahami makna bahasa secara benar. Kata atau
frasa yang bermunculan di layar digital tidak selalu menunjukkan kemajuan
intelektualitas bahasa. Ini karena secara terminologi bahasa harus juga dipahami
asal-usul kata atau frasa, tetapiionisnya sebagian besar masyarakat tidak peduli
dengan hal-hal semacam ini.
Berdasarkan
data tahun lalu, sebagaimana disampaikan oleh seorang peneliti dan pakar
linguistik Universitas Negeri Malang, Prof. A. Effendi Kadarisman. M.A, Ph.D,
dalam uji banding penulisan karya sastra dan penggunaan literasi berdasarkan
fungsinya bahwa ada konsep pemikiran yang terlepas atau ingin melepaskan diri
dari keterbelakangan pemahaman masyarakat tentang bahasa. Sebagian besar
masyarakat belum melek literasi
digital, tetapi sangat bergantung pada teknologi digital. Hal ini juga dapat
berbanding lurus dengan keberadaan karya-karya sastra yang mungkin mulai
meninggalkan akar pohonnya. Faktanya, karya sastra yang dihasilkan belum mampu
mengangkat minat baca terhadap karya sastra tersebut.
Hal itu
menyebabkan muncul beberapa polemik tatkala sastra masuk kurikulum . Apakah ini
sebuah polarisasi dalam edukasi sastra yang enggan memberi kesempatan kepada
generasi muda kini? Atau karena pegiat sastra itu sendiri kehilangan cinta pada
ruh dan jiwa sastra sebagai nilai seni yang harus dilakukan revitalisasi? Ini
mungkin bagai buah simalakama.
Sejatinya,
dalam kehidupan masyarakat, karya sastra berfungsi memberikan hiburan (rekreatif);
sastra mengarahkan atau mendidik pembacanya kepada nilai-nilai kebenaran dan
kebaikan (didaktif); sastra memberikan keindahan kepada penikmat atau pembaca (estetis);
sastra mampu memberikan pengetahuan tentang moral kepada pembaca atau penikmat
(moralitas); serta sastra menghasilkan karya-karya yang mengandung ajaran agama
(religius).
Sejarah pasti akan meninggalkan sebuah jejak, meski
perjalanan waktu tak dapat dibendung. Catatan budaya adalah peninggalan
literasi dan bahasa yang tak bisa dihilangkan. Sastra sebagai subjektivitas
pemikiran selalu berorientasi pada nilai-nilai bahasa yang mereduksi
perkembangan masa dengan menggunakan perpaduan kata-kata personifikasi,
hiperbola, metafora, dan lain-lain sebagai frasa kehidupan fiksi dalam konteks
nyata.
Intelektualitas
sastra harus dimaknai dalam karya-karya sastra yang telah melalui seleksi alam
secara ketat. Sastra bukan sebuah karya yang melegalkan istilah “nyastra tapi bukan sastra” dari pengakuan individu yang sangat tidak
objektif. Ini tentu juga sebagai perenungan di dunia pendidikan, sejauh mana kemampuan
para pendidik dalam melakukan transformasi keilmuan sastra dalam membentuk
karakter dan perilaku positif bagi peserta didik.
Kalau melihat
judul di atas, mengapa harus sastra yang memiliki kajian intelektualitas?
Apakah budaya juga bukan terlahir dan berkembang sesuai konsep kemajuan zaman?
Dengan kata lain, budaya menjadi kumpulan pemikiran yang memiliki nilai murni
atau hakiki untuk keseimbangan humanisme (kemanusiaan). Jika kita tempatkan pada
tembok putih masa sekarang, budaya seharusnya sudah mengalami reinkarnasi (kelahiran kembali). Dalam
arti, budaya bukan hanya dilihat sebagai satu konsep adat istiadat lokal. Kita
juga harus memperhatikan adat ialah sebuah gagasan kebudayaan yang menyangkut
norma, nilai-nilai dan kebiasaan pada suatu daerah, ermasuk juga memuat bahasa
daerah setempat. Pelestarian budaya lokal juga dapat dilakukan melalui
karya-karya sastra berbahasa daerah.
Seiring
perjalanan kehidupan, sastra tentu juga tidak akan terpisahkan dari ketajaman
mata budaya agar bisa melahirkan warna yang mampu mereduksi tantangan zaman. Saat
ini, banyak pelaku sastra belajar secara autodidak. Hal ini tentu harus
disadari oleh para pegiat sastra yang tidak boleh melupakan keberadaannya untuk
meningkatkan kualitas intelektual melalui penajaman pemahaman literasi dan
bahasa. Berdasarkan beberapa riset, masih banyak ditemukan para pegiat sastra
yang masih rancu dalam menggunakan bahasa.
Literasi sastra seharusnya mampu membentuk
perilaku positif bagi pembaca. Ada banyak kerancuan pada karya sastra yang
lebih menonjolkan sisi emosional, cenderung menampilkan sosok karakter penulis
atau pegiat sastra, tanpa mempertimbangkan aspek etika moral sebagai satu
kesatuan yang melekat dalam nilai budaya. Sebetulnya sangat sederhana, prinsip
dasar dalam literasi sastra adalah kuasai bahasa.
Lalu,
bagaimana dengan konsep intelektualitas sastra sebagai cermin manifestasi
bahasa? Pada sebuah sisi, jika kita mau jujur, kita dihadapkan oleh sebuah
problem ancaman era globalisasi yang muncul dalam bentuk isu-isu sosial sehingga
kita dihadapkan oleh sebuah ketakutan yang luar biasa. Peran sastra sebagai
sebuah ilmu mampu “menajamkan diri”
atau lebih bermartabat jika dianggap sebagai sebuah intelektualitas dalam
manifestasi bahasa. Sastra sebagai subjektivitas
pemikiran dalam dinamikanya begitu sulit untuk menjadi sebuah industri. Akan tetapi,
sumbangsih pemikiran sastra harus mampu menjadi generalisasi pemikiranyang
mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tentu sastra tidak
meninggalkan peran nilai humanisme (kemanusiaan).
Nilai sastra yang berkualitas tentu tidak meninggalkan peran bahasa sebagai
jembatan untuk membaca zaman.
Sebuah intelektualitas tentunya memiliki
nilai ukur yang jelas. Akan tetapi, ini cukup sulit karena sastra merupakan
sebuah dimensi imajinasi subjektivitas pemikiran yang selalu dihadapkan dengan
pilihan sulit untuk mengukur kualitasnya. Problem ini sering menjadi perspektif
yang berbeda pada masyarakat karena memandang karya sastra terlahir dari para
sastrawan yang telah memiliki nama besar. Kematangan dalam penguasaan literasi
dan bahasa seharusnya menjadi salah satu standar rumusan bagi kehidupan sastra
ke depan sehingga nilai intelektualitas semakin dapat diukur. *****
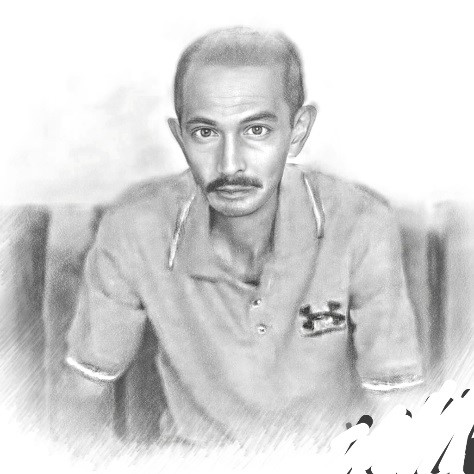
Vito Prasetyo
Penulis adalah sastrawan dan peminat bahasa, tinggal di Malang
