Bahasa dan Negara Paripurna: Merunut Akar Pemikiran Yudi Latif
Baru-baru ini, buku Yudi Latif yang berjudul Negara Paripurna terbit dalam cetakan kesepuluh (Juli 2024).
Cetakan ini agaknya lebih berharga dengan sampul bergambar bendera Merah Putih pada
awan yang tampak bergejolak. Juga, amat berharga dua hal pada bagian awal untuk
merunut akar pemikiran Pancasila: (1) ihwal bangsa yang mendahului negara dan
(2) bahasa Indonesia yang tercipta sebagai bahasa bersama.
Bagian Prolog dalam buku Yudi Latif yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama tersebut merupakan sambutan hangat dari Franz Magnis-Suseno. Sebagai catatan awal, atas terbitnya buku bacaan dengan subjudul Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila itu, penghargaan yang sangat tinggi telah diberikan oleh tokoh agama dan budaya tersebut dengan menuliskan sambutan bertajuk “Tambang Emas bagi yang Ingin Mengerti Indonesia”. Dengan mengambil hikmah relasi antara agama dan negara Pancasila, buku yang tebalnya lebih dari 700 halaman itu perlu digali informasi pentingnya hubungan pendasaran antara bahasa dan negara dimaksud.
Tata letak dasar bahasa Indonesia
Makna Indonesia
telah secara paripurna merujuk pada ciri khas sebuah bangsa. Oleh Soekarno, pemaknaan
bangsa Indonesia kerap dibuat dengan merunut definisi Otto Bauer: “die aus einer Schicksalsgemeinschaft erwachsende
Charaktergemeinschaft”. Franz Magnis menerjemahkannya dengan memadankan pengertian
‘komunitas karakter yang berkembang dari komunitas pengalaman bersama’. Dengan
tegas, ia berkata, “Indonesia adalah komunitas pengalaman bersama”.
Lebih lanjut, Franz Magnis pun bertanya, “Apa
yang membuat keanekaan etnik, budaya, ras, dan agama yang menghuni wilayah
kepulauan Nusantara antara Sabang dan Merauke sampai menjadi satu negara?” Ia mengakui
bahwa bahasa Indonesia merupakan sarana bekerja sama “mendalamkan kesadaran
nasional rakyat Indonesia”. Namun, sebagai bahasa bersama—dalam
pengakuannya—bahasa Indonesia “tidak
meletakkan dasar kebangsaan”.
Memang, perlu kepadaan eksplanatori (expalanatory adequacy) atas peristiwa Sumpah Pemuda 1928 yang mengikrarkan atau menjadikan kebulatan tekad satu bangsa. Peristiwa akbar 17 tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu tentu tidak terjadi di dalam ruang kosong (vakum) tanpa berisi peristiwa kebahasaan sebelumnya sebagai dasar kebangsaan tersebut. Tentu saja, masih ada persoalan teknis dengan pandangan Frans Magnis dan—mungkin—paham dari sebagian besar pembaca buku dalam hal terpilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia oleh kaum muda (kelas intelegensia Indonesia dalam istilah Yudi Latif) pada saat itu.
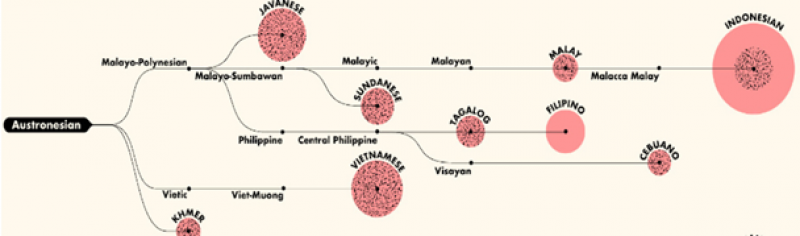
Persoalan teknis dimaksud ialah tata letak dasar bahasa Indonesia. Sebagaimana
terlihat pada gambar di atas (https://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/),
dasar bahasa bersama yang diikrarkan dalam teks Sumpah Pemuda tersebut masih
diletakkan setelah titik pusat peradaban Melayu (Selat) Malaka. Dengan tata
letak seperti itu, bahasa Indonesia (Indonesian)
belum memperlihatkan kedalaman dasar kebangsaan sebagaimana dimaksud dengan uraian
Yudi Latif mengenai pergerakan nasionalisme purba
yang berkembang melewati nasionalisme tua
untuk menuju nasionalisme modern.
Tata letak dasar bahasa Indonesia sudah semestinya mengikuti arah tahapan perkembangan
nasionalisme yang sangat lengkap diuraikan Yudi Latif itu.
Ketika dasar bahasa Indonesia diletakkan pada titik awal bergeraknya nasionalisme
modern, buku Negara Paripurna (baca halaman
143--144) sangat eksplisit menyebutkan asal mula pergerakan sosial itu dari
ujung barat Nusantara di sekitar Aceh, misalnya melalui Kerajaan Samudera Pasai.
Ketika itu, pengaruh Islam “secara cepat meluas ke bagian Timur meresapi
wilayah-wilayah yang sebelumnya dipengaruhi Hindu-Buddha”. Yang juga menarik
untuk dicatat dari buku itu ialah bahwa akselerasi atau percepatan kehadiran
Islam di kawasan Nusantara justru terjadi oleh karena penetrasi kekuatan Eropa,
yaitu kehadiran Portugis pada abad ke-16 dengan Belanda dan Inggris sebagai
pengikutnya.
Aktor utama kekuatan Eropa itu “tidak pelak lagi adalah Belanda”.
Demikan Yudi Latif berkata, sembari menunjukkan fakta historis kedatangan
Belanda dengan adanya armada perdana yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman
pada 1596 dan diikuti oleh operator Serikat Perseroan Hindia Belanda atau Vereenigde
Oostindische Compagnie (VOC) pada 1602. Pergerakan nasionalisme modern dari ujung barat di kawasan Nusantara
yang berkeindonesiaan itu dipelopori oleh perempuan pejuang Aceh. Adalah Laksamana
Malahayati (Keumalahayati), yang gigih berjuang membebaskan bangsanya dari cengkeraman
hegemoni penjelajah atau penjajah asing. Fakta historis kepeloporan
Aceh ini merupakan catatan penting untuk buku Yudi Latif.
Cornelis de Houtman memang tewas di tangan Laksamana Malahayati dalam duel satu lawan satu pada 11 September 1599 di atas geladak kapal armada Belanda itu. Akan tetapi, sebagaimana dipaparkan oleh Suratminto (2012 dalam Maryanto, 2023), Frederick de Houtman dibiarkan hidup dalam penjara selama 26 bulan di Benteng Pidi, Aceh. Di dalam penjara itulah disusun kamus bahasa kerja untuk percakapan sehari-hari dalam bentuk huruf latin seperti ini (https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/4117/keluhuran-bahasa-indonesia-dan-legasi-malahayati-di-unesco). “Appa bowat pagy hary bankit? Lagy poysa kamoe?” Kamus Frederick de Houtman yang terbit pada 1603 di Amsterdam itu tercatat paling tua dalam perjalanan sejarah pembentukan bahasa Indonesia. Kamus tertua itu menjelaskan tata letak dasar terbentuknya bahasa Indonesia pada masa pergerakan nasionalisme modern.
Rekonstruksi bahasa demi sesama bangsa
Lalu, bagaimana tata letak dasar bahasa
Indonesia pada masa pergerakan nasionalisme purba? Demi sesama bangsa yang
bermaujud Indonesia, bahasa persatuan sebagaimana ikrar Sumpah Pemuda 1928 itu masih
perlu direkonstruksi atau ditata ulang pada dasarnya untuk meletakkan landasan
berpikir tentang negara bangsa yang paripurna ini. Ulasan buku ini hendak
mendukung pandangan “Indonesia bukanlah sekadar kelanjutan
administratif bekas jajahan Belanda” sebagaimana dinyatakan oleh Franz
Magnis-Suseno dalam buku Yudi Latif tersebut. Benar bahwa dasar bahasa
Indonesia pun masih terlalu dangkal untuk menggambarkan pijakan berbangsa yang
satu itu apabila dilihat hanya dari jejak kebahasaan yang ditinggalkan oleh penjelajah
atau penjajah asing.
Jejak historis tersebut—sekalipun penting dan menarik—tentu
belum memadai untuk dijadikan data kebahasaan guna mendeskripsikan bahasa
Indonesia sebagai dasar kebangsaannya. Dengan melakukan pengamatan atau
observasi kebahasaan yang memadai terhadap keberadaan “komunitas pengalaman
bersama” di kawasan Nusantara, kepadaan deskriptif (descriptive adequacy) dapat diperoleh atas fakta bahasa yang
bekerja pada atau dipekerjakan oleh komunitas dimaksud sejak bergeraknya nasionalisme
purba. Atas dasar kebahasaan ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang
fakta keberadaan bangsa Indonesia yang jauh mendahului keberadaan negaranya.
Untuk memperoleh pemahaman yang amat mendalam, memang perlu ditelusuri petunjuk keberadaan bahasa (persatuan) Indonesia pada setiap titik pusat peradaban manusia Nusantara dari ujung timur hingga ujung barat. Untuk itu, wacana Negara Paripurna telah menuntun pembangunan konteks terkait narasi pergerakan nasionalisme modern dari ujung barat. Dari sini, wilayah Nusantara yang berkeindonesiaan perlu terlebih dahulu dipilah secara tegas perbedaannya dari kawasan yang tak-berkeindonsiaan. Dengan berbasis data kebahasaan, sebagaimana terbaca dari lembar informasi berikut, pemilahan dua wilayah Nusantara tersebut dapat dilakukan lebih tegas.

Dari lembar informasi kegiatan keilmuan antarbangsa itu, data kebahasaan
seperti bentuk dan pilihan kata (Jun bukan
Juni; Julai bukan Juli; Ogos bukan Agustus; dan yuran bukan iuran) dapat diperoleh sebagai bukti
pendukung atas keberadaan Indonesia yang di dalam buku Yudi Latif telah disebutkan
sebagai “komunitas pengalaman [dengan bahasa] bersama”. Kebersamaan yang
mewujudkan sesama bangsa Indonesia itu berbeda halnya dari komunitas bangsa di
negara tetangga, antara lain karena keberbedaan pengaruh asing. Oleh karena
itu, bahasa (asing) Belanda—melalui sistem tata bahasa (ejaan) van Ophuijsen—terbukti
telah ikut berpengaruh besar pada bahasa Indonesia.
Sementara itu, bahasa (asing) Inggris--melalui sistem ejaan Wilkinson—terbukti
telah turut membentuk bahasa negara tetangga Indonesia. Bahasa tetangga itu—walaupun
sangat dekat kekerabatannya dengan bahasa Indonesia—juga merupakan bahasa asing
dan bukan merupakan bahasa daerah bagi komunitas bangsa Indonesia. Ketentuan tiga jenis bahasa itu,
yaitu bahasa Indonesia, daerah, dan asing, telah diatur dalam Undang-Undang No.
24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan (Pasal 1). Di antara empat simbol kedaulatan dan kehormatan negara
itu, bahasa Indonesia tampak lebih menunjukkan pengaturan wujud eksistensi
bangsa Indonesia karena begitu lekat dan tak-berjaraknya simbol bahasa tersebut
dengan insan bangsa Indonesia selaku pemilik simbol.
Berikut adalah
ketentuan definisi tiga jenis bahasa tersebut. (1) Bahasa Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa
resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. (2) Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun
oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. (3) Bahasa asing adalah bahasa
selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Termasuk dalam kategori bahasa asing
itu adalah bahasa resmi di negara tetangga, baik yang terdekat dengan maupun
yang terjauh dari wilayah Indonesia.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, untuk
mengikuti kegiatan Persidangan Antarbangsa Peristilahan (Perantis) 2024 di
negara tetangga itu, warga negara Indonesia—siapa pun—tidak dapat menulis makalah
ilmiahnya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Untuk mengikuti
kegiatan itu, akademisi Indonesia harus menulis karya ilmiahnya dengan
memanfaatkan bahasa persidangan yang ditawarkan oleh penyelenggara kegiatan
tersebut sebagai bahasa asing. Pemanfaatan bahasa asing itu merupakan bentuk
pengakuan atas simbol kedaulatan dan kehormatan negara lain yang berkelindan
dengan pentingnya pengenalan simbol bahasa (negara) Indonesia.
Selain begitu pentingnya peran beragam bahasa asing itu, dalam rangka
menemu-kenali keberadaan bahasa Indonesia, juga terdapat aneka bahasa daerah yang
tidak kalah pentingnya untuk menelusuri landasan bahasa persatuan ini pada masa
purbanya. Keanekaan bahasa daerah ini dapat dilihat kesamaannya melalui
pembuktian secara empiris, antara lain, dari keberagaman atas ekspresi
kepemilikan -nya dalam bahasa
Indonesia. Keberagaman dimaksud benar-benar ada sebagaimana penggunaan bentuk
kepemilikan ni dalam bahasa Tarfia
dan Tobati di Papua serta bahasa Alor di Nusa Tenggara Timur. Makin kaya
keberagaman itu dengan bentuk ne
dalam bahasa Dubu, de dalam bahasa
Namblong, ge dalam bahasa Gresi, dan gi dalam bahasa Kafoa di Papua (baca
Mahsun, 2010: 199—202).
Semua variasi bentuk bahasa daerah (di) Indonesia merupakan refleksi kontruksi
dari satu sumber bahasa purba *nia dalam hal pengungkap milik (Nothofer,
1990 dalam Mahsun, 2010: 198). Peran bahasa daerah tersebut tentu sangat sentral
dalam merekonstruksi penyangga bahasa negara bangsa ini atas dasar bahasa purbanya,
terutama atas kekayaan bahasa daerah pada ujung timur Nusantara di Papua. Konstruksi
dasar bahasa Indonesia tersebut telah berhasil ditemu-kenali dalam bahasa (purba)
Austronesia atau—lebih lazimnya—bahasa Proto-Austronesia
yang disingkat sebagai PAN yang ditemukan
bersumber langsung dari atau berkerabat dekat dengan bahasa(-bahasa)
Trans-Papua.
Pada hari ini, diketahui bahwa masyarakat/guyub bahasa Indonesia teridentifikasi atas dua kelompok terbesar, baik penutur bahasa-bahasa PAN maupun Trans-Papua, yang terbukti telah mengalami proses baur padu pada masa bergeraknya nasionalisme purba secara kebahasaan. Bahasa Austronesia dihipotesiskan telah hidup sebagai bahasa kerja bersama pada 4.000-an tahun silam. Hipotesis itu baru-baru ini dibuktikan oleh Aron M. Mbete dalam webinar BRIN pada 29 Mei 2024 dengan mengungkap kemiripan/kesamaan bentuk dan makna asal pada kata yang berkerabat dalam bahasa PAN dengan bahasa Trans-Papua.

Dari
informasi yang disajikan dalam pertemuan ilmiah di BRIN itu, percontohan data kebahasaan dapat diambil, antara
lain, dalam bentuk kata one ‘rumah’
pada bahasa Lio di daerah Flores yang mirip dengan kata honey ‘rumah’ di Papua. Kaji-banding kebahasaan pun terbuka untuk
leksikon nama asli (orang dan toponimi) seperti kata wangge yang dapat dibandingkan dengan kata wanggai di Papua. Dalam kaji-banding sejarah bahasa itu, Mbete
mengungkap kembali pandangan Fishman (1968) yang menyebutkan bahwa nasionalisme
kebahasaan di Indonesia disangga kuat dengan keberadaan bahasa daerah beserta
unsur susastranya.
Aron M.
Mbete telah mengonfirmasi adanya relasi kekerabatan para penutur bahasa moyang dari turunan PAN dengan
sedemikian pula dekatnya relasi itu dari turunan bahasa Trans-Papua purba. Menurut hasil kajian Mbete, semua
bahasa yang hidup dan pernah hidup dapat dipastikan “menyatu dengan manusia sebagai makhluk yang berbicara dan bergerak
[bermigrasi] bebas ke mana-mana”. Oleh karena pergerakan atau perpindahan manusia
itu, mafhumlah
rakyat Indonesia merupakan komunitas/masyarakat majemuk dan multi-agama di
belahan bumi yang disebut-sebut sebagai kawasan Nusantara atau—oleh penulis
Barat—secara luas dikenalnya sebagai Hindia Timur atau—lebih spesifiknya—Hindia
Belanda.
Di dalam buku Yudi Latif, dijelaskan pula bahwa apa yang disebut sebagai Nusantara
(yang berkeindonesiaan sebagai satu negara bangsa) adalah sebuah wilayah
geografis dan sosiologis yang pada 8000 Sebelum Masehi sudah melimpah kekayaan
alamnya untuk memakmurkan penghuni bumi. Berlimpahnya kekayaan Nusantara itu menimbulkan
migrasi penduduk melalui kegiatan perdagangan yang mencapai puncak masa tuanya dari
masa pergerakan nasionalisme purba itu pada abad ke-16 ketika pedagang Eropa
memasuki kawasan Nusantara. Pada abad dimulainya pergerakan nasionalisme modern
inilah terjadi transformasi sosial-kebahasaan yang menuju terbentuknya
konstruksi dasar untuk berpikir paripurna tetang tiga jenis bahasa: Indonesia,
daerah, dan asing.
Pada bagian ini telah ditegaskan bahwa demi terwujudnya sesama bangsa
Indonesia, bahasa Indonesia selama masa pergerakan nasionalisme modern perlu
dilihat konstruksi dasarnya dari transformasi sosial-kebahasaan atas bahasa
asing (Arab, Inggris, Belanda, dan lain-lain) yang dibentuk oleh dan—sekaligus—membentuk
bahasa (persatuan bangsa) Indonesia. Sementara itu, bahasa daerah yang dikenal sekarang ini juga
bertransformasi dari landasan bahasa purbanya. Konstruksi dasar kebangsaan itu semuanya
tertelusur dengan narasi pergerakan nasionalisme secara kebahasaan pada masa purba
hingga masa tuanya, tentu dengan sebuah titik temu pergerakan sosial itu di
Barus (sekarang sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah).
Barus
sebagai titik arus balik peradaban
Tiga jenis bahasa—Indonesia, daerah, dan asing—pada abad XXI tengah
dilakukan konsolidasi trigatra bangun bahasa
berdasarkan amanat Undang-Undang No. Tahun 2009. Utamakan bahasa
Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Begitulah rumusan spirit pembangunan nasional
dalam bidang bahasa (negara bangsa) Indonesia dewasa ini pada abad konsolidasi
yang terhitung mulai tanggal ditetapkannya peraturan perundang-undangan itu.
Abad konsolidasi kebahasaan ini berlangsung dalam sebuah arus globalisasi yang—berdasarkan
bacaan Yudi Latif—ternyata peradabannya telah dirintis oleh nenek moyang bangsa
Indonesia.
Dalam buku Negara Paripurna (secara
khusus pada bab ketiga tentang kemanusiaan universal) Yudi Latif memang menyata-tegaskan
bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan perintis globalisasi purba (archaic globalization). Arus peradaban
global di Nusantara ditegaskan dalam buku itu prosesnya melalui penjelajahan
samudra dengan kekuatan maritim yang jaya pada saat kontak antar-benua yang berbasis
kelautan. Penulis buku tersebut menyatakan, “Jalur pelayaran Samudra Hindia
[Samudra Indonesia] bukan saja merupakan pusat transaksi perdagangan, melainkan
juga pusat persilangan pengetahuan.” Sebuah titik pusat persilangan dimaksud ialah
kota kuno Barus.
Kota perdagangan internasional pertama di kawasan Nusantara itu layak
dirujuk atas ungkapan Yudi Latif “arus balik: globalisasi di Nusantara”. Dari kota
kuno itulah, terlihat titik arus baliknya dan begitu strategisnya peran bahasa
sebagai penghela (ilmu) pengetahuan ketika ada nilai kebaruan yang masuk ke kawasan
Nusantara yang berkeindonesiaan. Penjelasan Yudi Latif tentang kemanusiaan
universal tersebut telah memerinci adanya nilai budaya dan agama yang dimasukkan,
baik dari India, Arab, Persia, Cina, maupun dari Eropa. Setengah orang dari keturunan
India, Arab, Persia, Cina, dan Eropa itu masing-masing boleh jadi merupakan
warga bangsa Indonesia. Namun, bahasa yang menghela masuknya nilai budaya dan
agama yang mereka bawa ke Indonesia itu tetap mengalami eksternalisasi melalui transformasi bahasa asing pada bangsa
Indonesia.
Sebaliknya, terdapat jalan internalisasi
dalam alam pemikiran Pancasila yang dikembangkan oleh Yudi Latif untuk
membangun konteks wacana Negara Paripurna.
Untuk itu, sejumlah bahasa (tidak kurang dari 718 bahasa)—termasuk di dalamnya bahasa
Melayu, Jawa, dan Sunda—telah mengalami internalisasi
melalui transformasi bahasa daerah dari landasan bahasa purbanya. Dengan menempuh
dua jalan—eksternalisasi dan internalisasi—untuk berpikir tentang negara
Pancasila, prinsip kebangsaan ini menjadi sangat luas karena pada satu sisi
mengarah pada persaudaraan dunia
dengan keluar secara bebas-aktif melalui penguasaan bahasa asing sebagaimana
terbentuknya tradisi budaya bersastra Melayu-Arab oleh sastrawan Barus, Hamzah
Fansuri, pada abad ke-16 (https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/4147/mengenang-abdul-hadi-w.m.:-dna-sastra-bangsa-indonesia-tertelusur-dari-barus).
Melalui jalan internalisasi dalam prinsip kebangsaan tersebut, pengakuan dan pemuliaan hak dasar warga bangsa Indonesia telah dilakukan secara nyata-nyata dengan melestarikan bahasa daerah. Seturut dengan alam pemikiran Pancasila, untuk menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh, diperlukan landasan yang merupakan prasyarat persaudaraan universal. Ihwal pentingnya landasan persaudaraan yang berkeindonesiaan itu dinyatakan oleh Yudi Latif sebagai berikut.
Jalan internalisasi atas nilai persaudaraan kemanusiaan tersebut membuat Indonesia menjadi negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan Indonesia yang berasal dari kebinekaan masyarakat Indonesia ini diwujudkan berdasarkan konsepsi kebangsaan yang diekspresikan dengan bahasa persatuan dalam keragaman bahasa daerah dan keragaman bahasa daerah dalam bahasa persatuan, seturut dengan slogan bernegara yang dinyatakan dengan ungkapan ”Bhinneka Tunggal Ika.”
Pada sisi
internalisasi itu, wawasan pluralisme berkembang pesat dalam alam pemikiran
Pancasila yang senantiasa menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka
perbedaan, termasuk bahasa daerah yang berbeda-beda, sebagai warisan nenek
moyang bangsa Indonesia. Semua ruang keberbedaan itu terisi dengan nilai
keutamaan satu bahasa kebangsaan Indonesia dan kelestarian segala bahasa daerah
yang ada di wilayah Indonesia. Sekadar untuk
ilustrasi pelestarian bahasa daerah yang tengah berlangsung, sebutlah sekarang
bahasa (daerah) Kaili di Sulawesi Tengah. Bahasa daerah ini merupakan modal sosial untuk kerja
bersama guna menjadikan sesama masyarakat Kaili, antara lain melalui kekayaan
ungkapan/peribahasa seperti nangelo belo ‘mencari baik’ dan belo rapovia belo rakava ‘baik dibuat baik didapat’.
Nilai dasar kehidupan sosial tersebut tentu merupakan karakter masyarakat
daerah Kaili yang setiap warganya diharapkan dapat selalu berbuat kebaikan agar kebaikan pula yang
didapatkan. Atas dasar hasil telaah kebahasaan,
sebagaimana dipaparkan oleh Deni
Karsana dalam webinar BRIN pada 29 Mei 2024, bahasa daerah
itu diketahui berasal dari induk bahasa Austronesia yang berkembang biak dan
tersebar luas dalam subrumpun Melayu Polinesia di
Sulawesi Tengah. Oleh karena fakta kebahasaan seperti itu, jauh sebelum berkembangnya bahasa Melayu-Arab di
Barus pada masa pembibitan bahasa (negara persatuan) Indonesia, bahasa (purba) Melayu
Polinesia dapat dikonfirmasi telah hidup secara berkelanjutan dari bahasa
Autronesia yang dapat direkonstruksi dasar kekerabatannya dengan bahasa
Trans-Papua purba.
Istilah globalisasi purba yang
dikembangkan oleh Yudi Latif tersebut berkesapadanan pengertiannya dengan arah gerakan
nasionalisme purba yang secara kebahasaan telah mencapai titik balik di Barus
ketika konsepsi persaudaraan dunia dalam prinsip kebangsaan itu mulai
berkembang di sana. Pada titik kedalaman dasar kebangsaan itu, persimpangan
dengan jalan eksternalisasi tersebut memberikan petunjuk atas jalan internalisasi
nilai berkeindonesiaan itu—sekali lagi dari perspektif kebahasaan—yang berbalik
arah dalam arus peradaban ke timur pada masa pergerakan nasionalisme modern.
Dari titik
perjumpaan—apa yang disebut oleh Yudi Latif dengan istilah kunci kemanusiaan universal—di Barus, arus
balik peradaban Nusantara yang berkeindonesiaan tersebut mencerminkan transformasi sosial-kebahasaan (bahasa
Indonesia, daerah, dan asing) seturut dengan asas tri-kon dari teori Ki Hadjar
Dewantara: kontinu, konsentris, dan konvergen. Bahasa negara bangsa yang secara
kontinu bertransformasi ini merupakan konsepsi kemanusiaan yang memiliki dasar
atau landasan konsentris atas bahasa purbanya dan berkonvergensi dalam
kesemestaan manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan YME (Allah Swt.).
Dalam wacana Negara Paripurna, sangat
menarik butir demi butir informasi dengan penjelasan Yudi Latif yang
dikonfirmasi oleh M. Dawam Rahardjo pada bagian penutup buku dengan tajuk
“Bagaimana Pancasila Menjadi Islam”. Pada bagian pengantar, Yudi Latif pun telah
terlebih dahulu menjelaskan bahwa buku yang beberapa kali direvisi dan dicetak
berkali-kali itu lahir atas usaha “mendarahi semangat inklusivisme Nurcholish
Madjid dengan mengembangkan pergaulan lintas batas”. Semangat Islam
yang inklusif itu ditemukan denyut pergerakannya lebih awal di kota kuno Barus
sebagai gerbang masuknya agama-agama (di) Nusantara (Tumanggor, 2017) yang
telah membawa hikmah/kebijaksanaan dalam hal bahasa Indonesia, daerah, dan
asing.
Konsolidasi trigatra bangun bahasa—bahasa Indonesia yang diutamakan; bahasa
daerah yang dilestarikan; dan bahasa asing yang dikuasai—merupakan sebuah
gerakan pembangunan nasional dalam aktualisasi nilai Pancasila. Dalam hal itu,
bacaan Negara Paripurna yang
diterbitkan baru-baru ini menjadi semacam “tambang emas” (dalam ungkapan Franz
Magnis-Suseno) untuk menelisik kebaruan realitas sejarah akan keberadaan bangsa
Indonesia yang secara kebahasaan benar-benar telah jauh mendahului keberadaan negaranya.
Pada abad konsolidasi kebahasaan ini sangatlah perlu untuk merunut akar
atau dasar bahasa (persatuan bangsa) Indonesia dari Barus hingga landasan
bahasa bersama ini pada masa purbanya demi Indonesia yang berkemajuan secara
paripurna. Cara berpikir mendasar tentang keindonesiaan itu terasa lebih dipermudah
oleh Yudi Latif dengan terbitnya buku Negara
Paripurna (cetakan kesepuluh) yang telah disambut sangat hangat untuk turut
menyemarakkan perayaan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Bangsa Indonesia sepanjang
Agustus 2024.
Nusantara baru; Indonesia maju! ---
Daftar Pustaka
Latif, Yudi. 2020. Pendidikan yang Berkebudayaan: Hostori,
Konsepsi, Aktualisasi Pendidikan Tranformatif. Jakarta: Gramedia.
__________. 2024. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas,
dan Aktualitas Pancasila (Cetakan Kesepuluh). Jakarta: Gramedia.
Madjid, Nuscholish. 2004. Indonesia Kita (Cetakan Keempat). Jakarta:
Universitas Paramadina.
Mahsun, 2010. Genolinguistik: Kolaborasi Linguistik dengan
Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Tumanggor, Rusmin. 2017. Gerbang agama-agama nusantara (Hindu, Yahudi, Konghucu, Islam &
Nasran): Kajian Antropologi Agama dan Kesehatan di Barus. Depok: Komunitas
Bambu.

Maryanto
Widyabasa Ahli Madya (Penghayat Trigatra Bangun Bahasa) Badan Bahasa, Kemendikbudristek
